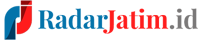Oleh DEWI MUSDALIFAH
Kejadian ini tidak akan menyandera pikiran saya, jika tidak terulang dua kali untuk hal yang nyaris sama.
Saya adalah salah seorang anggota organisasi perempuan yang cukup punya nama. Keberadaan saya di organisasi ini, awalnya karena “kejahilan” teman yang memasukkan saya ke dalam struktur organisasi tersebut.
Salah satu momentum yang bikin gemes sekaligus kesal, ketika organisasi ini mendapat amanah oleh struktur wilayah untuk menyelanggarakan sebuah perhelatan. Kebetulan saya tidak terlibat langsung sebagai panitia. Namun, suatu hari dihubungi ketua bagian –dalam lembaga yang sama– untuk membantu memandu operator videotron dalam acara itu.
Karena tahu tugas itu sangat penting, yakni memberikan petunjuk dan menyiapkan materi tayang, maka saya pun bersedia menerima tugas itu. Pada hari H pelaksanaan, saya pun datang ke gedung acara tersebut dengan memakai baju batik biasa, karena memang tidak memiliki seragam sebagai panitia.
Semua tugas saya laksanakan dengan baik.Tugas itu, mulai dari menata tayangan pertama, videonya apa, tayangan berikutnya slide-nya bagaimana, sampai menghubungi pemateri yang ternyata tidak sesuai jadwal, bahkan materinya tidak sama. Saya harus bolak-balik berlari-lari ke samping panggung untuk menghubungi MC untu mennyesuaikan materi.
Di saat saya masih berkeringat karena kesibukan itu, datang salah satu pimpinan organisasi menghampiri dan bertanya, “Ngapain di tempat ini?” Saya jelaskan, saya dimintai tolong panitia untuk memandu operator videotron.
Seusai acara tersebut, sampailah acara foto bersama. Seluruh panitia diminta foto di atas panggung. Karena saya tidak merasa jadi panita, otomatis tidak maju ke depan. Tapi, beberapa teman menyeret saya untuk ikut foto bersama, karena menganggap telah menjadi bagian dari mereka dan dinilai telah bekerja keras memandu tayangan videotron hingga berjalan mulus.
Ketika saya berada di barisan panitia untuk foto bersama, tiba-tiba pimpinan tadi menghampiri dan mendorong saya untuk keluar dari barisan. Itu ia lakjukan karena saya tidak memakai seragam panitia. Foto bersama hanya diperuntukkan bagi yang memakai seragam yang sama.
Saya tersenyum saja dan mundur perlahan dengan menahan nafas. Kemudian saya memesan grabcar untuk pulang. Peristiwa itu membuat saya kecewa, namun terlupakan begitu saja.
Terulang Lagi
Kejadian itu terulang kembali. Suatu saat saya ditunjuk menjadi ketua panitia dalam acara organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri atas kaum Adam. Dan, saya juga salah seorang anggota perempuan yang termasuk di dalamnya. Selain ketua panitia, saya merangkap sebagai MC yang mengantarkan acara itu mulai awal sampai akhir.
Di dalam acara tersebut juga mengundang organisasi perempuan yang saya pun menjadi anggotanya. Mereka datang dengan memakai seragam kebesarannya. Hanya saja saya tidak memakai seragam organisasi perempuan tersebut, tetapi memakai seragam organisasi yang terdiri dari bapak-bapak yang menjadi tuan rumah acara tersebut.
Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Saat acara usai, saya bersiap beranjak untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah membantu kelancaran acara. Saat hendak berjalan, seperti biasa teman-teman organisasi perempuan itu berfoto ria. Kembali mereka menarik saya untuk ikut foto bersama, karena merasa saya bagian dari mereka. Hanya saja, dalam acara ini saya berperan dalam organisasi yang berbeda, namun masih satu tubuh organisasi besar.
Secara reflek saya pun menurutinya. Namun, sekali lagi pimpinan organisasi perempuan itu menolak saya dengan kasar di hadapan semua anggota dengan dalih, saya tidak memakai seragam yang sama dengan mereka.
Dengan perasaan tidak enak saya hengkang dari panggung dan meneruskan kegiatan menuju tim untuk berbenah. Seketika itu saya flashback mengingat kembali perjalanan di organisasi perempuan tersebut. Selama ini saya memang melihat ada banyak kejanggalan. Di setiap momen kegiatannya, selalu yang dikedepankan adalah memakai seragam apa, dan foto selfie menjadi prioritas kebiasaan mereka.
Semua seakan akan diseragamkan. Begitu juga pemikiran anggota. Potensi-potensi terbaik anggota tidak dikelola dengan baik. Hampir di seluruh kegiatan berisi materi pengulangan yang sama, tanpa ada pembaharuan ide. Bahkan, upgrading pemikiran pun tidak terjadi di organisasi ini.
Pembicaraan cenderung didominasi tema yang sama, yang menurun dari atas ke bawah (top down) dan hanya doktrin. Padahal, sebagai organisasi perempuan yang memiliki tanggung jawab pendidikan kepada generasi yang akan datang, mestilah bergerak maju dengan pemikiran yang maju pula, serta visioner.
Orientasinya bukan lagi pada bagusnya kemasan di luar, tetapi seberapa besar peran kita membuat perubahan bagi lingkungan. Perubahan itu terutama bagi pemberdayaan perempuan dalam kaitannya mendidik generasi milenial.
Saat ini, kaum mileniallah yang sedang kita hadapi dan didik. Sudahkah kita memahami dunia mereka? Mesti ada upaya untuk mengadaptasi konten komunikasi agar bisa diterima oleh generasi ini. Kita mesti menjadi akar yang tetap terus bertahan dan tidak ditinggalkan.
Ini tentu saja tidak mudah. Peningkatan kualitas diri anggotanya harus mumpuni. Ia harus terus diasah dengan memaksimalkan keberagaman potensi untuk bisa maksimal berperan sesuai kadar masing masing.
Perempuan identik dengan keindahan, bukan hanya dalam hal berbusana, namun keindahan dalam pemeranan juga faktor penting untuk mengisi peran kebangsaan. Ah, perempuan! (*)
*) Penulis adalah pegiat pustaka dan sastra, tinggal di Gresik, Jawa Timur