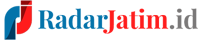Oleh: Moh. Husen*
Pada minggu terakhir bulan Oktober 2024, hari-hari saya kerap bertemu dengan teman-teman penyair. Semua ini sebenarnya karena saya “ngefans” sama Emha Ainun Nadjib. Akhirnya saya “mambu-mambu” dunia sastra.
Ah, tapi begini. Saya mau muter-muter dulu.
Kalau suatu hari ada orang melihat saya ke warung kopi menggunakan kaos oblong berwarna putih, mohon jangan disimpulkan kaos yang saya punya dan selalu saya pakai adalah kaos berwarna putih.
Atau jika setiap hari Minggu saya menggunakan kaos putih, dan banyak orang hanya ketemu saya pas hari Minggu saja: mohon jangan punya pemahaman bahwa saya identik dengan kaos putih.
Apalagi dalam hal menulis. Mohon jangan menyimpulkan saya berani “membenci” dan “mentalak tiga” penguasa hanya karena saya sering menulis tentang warung kopi dan warung kopi.
Untunglah saya bukan seorang penulis puisi cinta, yang bisa diartikan karena sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, mending nulis tentang cinta aja deh. Dianggap lebay juga nggak apa-apa.
Artinya, orang menulis puisi cinta kepada lawan jenis bisa kita tuduh sedang jengkel kepada pemerintah. Dia mengkritik keras dan nyata dengan cara meninggalkannya dan pergi ke dunia puisi cinta.
Tapi, iya kalau dianggap jengkel kepada pemerintah. Kalau dianggap sebagai penyair salon, gimana dong?
Jawabannya gampang: salahnya sendiri merasa jadi penyair. Nulis puisi ya nulis puisi saja. Baca puisi ya baca puisi saja. Begitu disebut penyair dan percaya betul bahwa ia penyair, maka ia akan marah kalau dianggap penyair salon.
Kritik kepada penyair itu bisa terjadi hanya kalau yang bersangkutan merasa jadi penyair. Kan yang dikritik penyair. Sedangkan semua orang bisa saja rajin baca puisi tapi merasa bukan penyair, sehingga kritik tersebut salah alamat.
Tentu yang saya sampaikan ini “ilmunya” Emha. Dia menjalani apa saja, tapi tidak terikat oleh identitas yang ia jalani. Cak Nun lebih bangga disebut manusia biasa saja. Tanpa embel-embel budayawan, seniman, penyair, sastrawan, apalagi kiai.
Semua ini saya paparkan agar para pembaca ada peluang mengejek saya: “Pemujanya Cak Nun nih ye…”
So, jangan pernah abaikan kritik orang lain melalui puisi WS Rendra mengenai fenomena penyair salon. Namun kita sendiri harus rajin berkaca: apakah kita termasuk penyair salon yang sibuk mempercantik diri sendiri tanpa peduli kemiskinan dan pengangguran?
Kalau saya jelas: penyair hari libur, alias libur karena tidak pernah menulis puisi dan apalagi membaca puisi. (*)
Banyuwangi, 3 November 2024
*Catatan kultural jurnalis RadarJatim.id, Moh. Husen. Tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur.