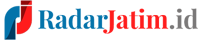Oleh Rokimdakas *)
Ketika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menertibkan bekas lokalisasi Dolly dari praktik prostitusi gelap, tindakannya seperti kebingungan membaca zaman. Betapa prostitusi telah bermetamorfosis secara digital, yang umumnya hotel dijadikan ruang eksekusi. Eri ibarat menonton perang dari belakang layar kaca, tetapi merasa sedang memimpin pasukan.
Ketika agama-agama besar –Yahudi, Kristen, Islam– menguat, pelacuran memasuki fase moral yang lebih rumit. Di satu sisi, ia dilarang karena dinilai tindakan dosa, namun di sisi lain dipertahankan sebagai “dosa yang diperlukan” untuk menghindari dosa yang lebih buruk.
Fenomena Paling Tua
Sejarah peradaban manusia adalah sejarah tentang kebutuhan, kekuasaan, dan cara manusia menata tubuhnya dalam struktur sosial. Dalam alur sejarah sepanjang itu, pelacuran muncul sebagai fenomena yang paling tua, paling bertahan, dan paling sulit diberantas.
Tidak ada satu pun peradaban besar yang luput dari kehadirannya, baik sebagai institusi ekonomi, ritual religi, maupun jaringan bawah tanah yang bertahan dalam perubahan zaman. Pelacuran bukanlah produk modern. Dalam masyarakat pra-sejarah, meski tidak terinstitusi, pertukaran seks untuk makanan atau perlindungan sudah terjadi.
Bukti paling jelas muncul pada peradaban Mesopotamia (3000–2000 SM), ketika pelacuran menjadi bagian dari praktik keagamaan dan ekonomi. Yunani mengembangkannya menjadi struktur sosial bertingkat, sementara Romawi memberinya status legal melalui registrasi resmi.
Di berbagai fase sejarah agama, pelacuran dikecam namun tetap dibiarkan “ada” sebagai kompromi moral. Ketika agama-agama besar —Yahudi, Kristen, Islam— menguat, pelacuran memasuki fase moral yang lebih rumit. Di satu sisi, ia dilarang sebagai dosa, namun di sisi lain ia dipertahankan sebagai “dosa yang diperlukan” untuk menghindari dosa yang lebih buruk.
Di dunia Islam klasik, larangan keras tidak membuat pelacuran hilang. Ia sekadar bergerak ke ruang-ruang lain melalui keberadaan qiyan, yaitu budak, penyanyi dan penghibur yang sering dikaitkan dengan layanan erotis. Dan, sampai sekarang banyak TKW Indonesia di Saudi Arabia dianggap budak yang bisa diperlakukan sesuka majikan, tidak terkecuali layanan seksual.
Fenomena ini menegaskan satu hal, bahwa pelacuran bukan penyimpangan sosial yang tiba-tiba lahir, tetapi efek samping dari sistem ekonomi, politik, dan moral suatu masyarakat.
Kebijakan Tak Menyentuh Akar Masalah
Beberapa tahun terakhir, Jawa Timur menjadi panggung besar bagi kampanye penutupan lokalisasi. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi berlomba mengumumkan “prestasi moral” dengan menutup prostitusi. Seolah sebuah kemenangan besar telah diraih: lokalisasi ditutup, papan nama diturunkan, dan bangunan-bangunan lama dialihfungsikan.
Namun ada jurang besar antara apa yang terlihat dan apa yang nyata. Secara statistik, penutupan lokalisasi memang memudahkan pejabat memamerkan keberhasilan. Tetapi, secara sosial dan kesehatan publik, kebijakan ini meninggalkan persoalan cukup kompleks. Ketika ruang terkonsentrasi dibubarkan, sistem pengawasan kesehatan ikut hilang.
Dulu, pekerja seks dalam lokalisasi dapat diuji kesehatan secara rutin, diberi edukasi tentang penyakit menular seksual (PMS), dipantau oleh Puskesmas lokal, juga dibantu relawan kesehatan, juga LSM. Kini, setelah lokalisasi “hilang”, apa yang terjadi?
Objek pengawasan itu lenyap. Para pramunikmat menyebar ke jaringan informal yang tidak terpetakan. Frekuensi pemeriksaan kesehatan menurun drastis. Kontak dengan tenaga medis pun makin jarang.
Pemerintah mungkin merasa puas karena lokalisasi tidak lagi nampak kasat mata, tetapi masyarakat justru menghadapi ancaman kesehatan yang lebih gelap. Di berbagai daerah di Indonesia, peningkatan kasus HIV/AIDS pascapenutupan lokalisasi sudah lama menjadi kekhawatiran para ahli kesehatan masyarakat. Sebabnya, penutupan membuat pekerja seks berpindah ke ruang-ruang tersembunyi, sehingga edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan tidak lagi terjangkau.
Pejabat boleh jadi tertawa-tawa dalam konferensi pers. Tetapi, masyarakat yang hidup dalam realitas sosial justru dihantui bencana yang tak bersuara.
Digitalisasi Prostitusi
Penutupan lokalisasi tidak menghentikan pelacuran. Ia hanya mendorongnya untuk bermetamorfosis. UKini di Jawa Timur, fenomenanya berubah drastis:
1. Prostitusi motor (mobile sex work). Pramunikmat menerima panggilan, bergerak dengan motor, dan menyelesaikan transaksi dalam hitungan jam. Tidak ada lokasi, tidak ada sentra, hanya jejak digital yang cepat dihapus.
2. Migrasi ke hotel-hotel kecil. Hotel-hotel mungil menjamur dengan tingkat okupansi mencurigakan tinggi. Tingginya tingkat hunian (okupansi) itu, bukan oleh wisatawan, tetapi aktivitas short time yang berlangsung nyaris berlangsung sepanjang hari. Kota nampak rapi, tetapi dinamika pelacuran justru berdenyut di ruang privat yang tertutup rapat dari regulasi.
3. Prostitusi berbasis aplikasi. Beroperasi melalui platform yang memfasilitasi pertemuan, pesan terenkripsi, atau kode internal. Bukan lagi lorong atau gang sempit, tetapi ruang virtual yang hampir mustahil dijangkau aparat.
Dengan kata lain, struktur pelacuran lama runtuh, tetapi jaringannya justru tumbuh lebih cepat dan lebih adaptif.
Ilusi Eri Cahyadi
Ketika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berencana menertibkan bekas lokalisasi Dolly dari praktik prostitusi gelap, kebijakan itu nampak seperti kebingungan membaca zaman. Menertibkan lokasi yang aktivitas prostitusinya sudah lama pindah ke ruang digital ibarat menonton perang dari belakang layar kaca, tetapi merasa sedang memimpin pasukan.
Kebijakan yang menyasar lokasi fisik hari ini hanya menyentuh kulit persoalan. Prostitusi modern tidak lagi stasioner. Ia cair, bergerak, dan bersembunyi dalam sistem yang tidak lagi mengenal batas wilayah.
Langkah Eri nampak seperti pahlawan kesiangan. Heroik dalam berita dan advetorial, tetapi secara realitas tidak relevan. Lebih parah lagi, sikap ini menciptakan ilusi bahwa pemerintah “berhasil” mengendalikan situasi, padahal justru gagal membaca metamorfose pelacuran yang terjadi di depan mata.
Sepanjang 5.000 tahun sejarah manusia, satu hal tidak pernah berubah, bahwa pelacuran tidak dapat dihapus, hanya dapat dikelola. Mengabaikan akar masalah hanya memperbesar dampak negatifnya.
Penutupan lokalisasi boleh nampak sebagai prestasi moral, tetapi menghilangkan sistem kontrol kesehatan. Ia memperluas penyebaran jaringan tak terpantau, mendorong praktik lebih tersembunyi dan berisiko. Dan, dampaknya membuka peluang lonjakan penyakit menular.
Dengan latar sejarah panjang ini, maka menjadi jelas, bahwa pelacuran bukan bisa dihapus hanya dengan kebijakan administratif. Yang bisa dilakukan adalah meminimalkan dampak buruknya melalui pendekatan kesehatan publik, regulasi manusiawi, edukasi, dan pembacaan terhadap dinamika digital.
Pelacuran, dari Mesopotamia hingga era aplikasi, adalah cermin kejujuran sosial. Ia tidak hilang saat ruangnya ditutup, melainkan hanya berganti bentuk. Kebijakan yang gagal memahami metamorfosenya hanya akan melahirkan bencana yang lebih tersembunyi.
Maka, yang hilang dari lokalisasi bukan prostitusinya, tetapi kemampuan kita untuk mengawasinya. Dan, di balik tawa pejabat yang memamerkan “prestasi”, masyarakat diam-diam diwarisi risiko kesehatan dan sosial yang semakin sulit dikendalikan. (*)
*) Rokimdakas, Jurnalis senior, tinggal di Surabaya.