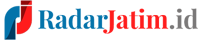Oleh Junaedi *
Seorang dosen senior di sebuah universitas ternama baru-baru ini bercerita tentang pengalaman yang menggelitik sekaligus memprihatinkan. Saat presentasi, seorang mahasiswanya tampil dengan paparan yang luar biasa canggih. Istilah-istilah akademis pun mengalir lancar, struktur argumennya nyaris rapi sempurna.
Namun ketika ditanya lebih dalam, sang mahasiswa nampak tergagap, tidak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia paparkan. “Berapa persen dari presentasi ini yang dibuat dengan AI?” tanya sang dosen. Mahasiswa itu mengaku: lebih dari separuh materinya dihasilkan oleh ChatGPT.
Kisah ini bukan sekadar anekdot. Ia adalah cermin dari tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) . Melalui Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan mulai tahun ajaran 2025/2026, yang diberlakukan dari kelas 5 SD hingga SMA.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan: “Manusia tidak akan digantikan oleh AI, tapi mereka yang tidak memanfaatkannya akan tertinggal.” Pernyataan ini memang benar, namun tidak utuh. Karena pertanyaan yang lebih mendasar adalah: bagaimana memanfaatkan AI tanpa kehilangan jati diri sebagai manusia yang berpikir?
Mari kita akui: potensi AI dalam pendidikan sangatlah besar. Teknologi ini mampu menjadi tutor personal yang sabar, siap 24 jam, dan dapat menyesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Di negara seperti Korea Selatan, buku teks digital berbasis AI telah mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan individual siswa.
ChatGPT dan sejenisnya dapat membantu siswa memahami konsep yang rumit, memberikan penjelasan alternatif ketika guru tidak tersedia, dan bahkan membantu mereka yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua untuk menulis lebih baik. Dalam survei lintas budaya, 61% siswa di negara-negara kolektivis, seperti Indonesia, menganggap ChatGPT dapat diterima sebagai asisten belajar.
Namun, di balik kemudahan itu tersimpan ancaman yang tidak boleh diremehkan. Penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan AI dalam mengerjakan tugas akademik telah mengubah bentuk plagiarisme. Dulu, siswa menyalin langsung dari sumber lain. Kini, mereka merangkai jawaban dari AI tanpa benar-benar memahami substansinya, sebuah praktik yang disebut “plagiarisme kain perca.” Yang lebih mengkhawatirkan, studi menemukan, bahwa siswa cenderung lebih permisif terhadap plagiarisme berbasis AI dibanding menyontek dari karya manusia lain. Seolah-olah karena mesin yang membuatnya, maka tidak ada yang dirugikan.
Dampak jangka panjangnya lebih serius: erosi kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Ketika siswa terbiasa mendapatkan jawaban instan dari AI, mereka kehilangan kesempatan untuk bergumul dengan ketidaktahuan, sebuah proses yang justru membentuk daya nalar. Seorang mahasiswa yang selalu mengandalkan ChatGPT untuk menulis esai tidak akan pernah mengalami frustrasi mencari kata yang tepat, yang justru melatih otaknya berpikir lebih dalam. Sebagaimana dikemukakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Guru Belajar, Maman Basyaiban, tantangan mendasar dalam kurikulum AI adalah bagaimana memastikan guru dan murid “tidak terjebak pada alat, melainkan pada cara berpikir.”
Di sinilah peran guru menjadi semakin penting, bukan semakin berkurang. AI tidak memiliki empati. AI tidak bisa membaca ekspresi wajah siswa yang kebingungan, namun malu bertanya. AI tidak mampu memberikan contoh keteladanan moral. Sebesar dan sehebat apa pun kemampuan AI, teknologi ini tidak dapat menggantikan bimbingan moral yang diberikan guru dalam proses pendidikan. Pendidikan sejatinya bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter, dan untuk itu, sentuhan manusia tidak tergantikan.
Tantangan lain yang tak kalah berat adalah kesenjangan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang stabil, komputer yang memadai, atau guru yang berkompeten dalam literasi digital. Sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap, akan lebih mudah mengadopsi teknologi ini. Sementara sekolah di daerah tertinggal, dapat dipastikan semakin jauh kedodoran. Pemerintah memang telah menyiapkan solusi “kurikulum unplugged” untuk sekolah tanpa akses digital —pembelajaran tanpa perangkat digital dalam bentuk permainan edukatif—, namun ini tetap memerlukan pelatihan guru yang masif dan merata.
Selanjutnya, bagaimana jalan keluarnya? Pertama, pendidikan etika digital harus menjadi fondasi sebelum siswa diperkenalkan pada AI. Siswa perlu memahami bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti otak mereka. Integritas akademik —kejujuran dalam mengerjakan tugas— harus ditanamkan sebagai nilai yang tidak bisa ditawar.
Kedua, metode asesmen perlu diubah. Ujian berbasis esai yang bisa dengan mudah dijawab AI mungkin perlu digantikan dengan presentasi lisan, diskusi mendalam, atau proyek kolaboratif yang menuntut pemahaman nyata.
Ketiga, guru harus dilatih tidak hanya untuk menggunakan teknologi, tetapi juga untuk mendeteksi penyalahgunaannya. Beberapa universitas di Australia telah kembali ke ujian berbasis kertas sebagai langkah mitigasi, sebuah respons yang mungkin terkesan mundur, namun sebenarnya sangat pragmatis.
Yang paling penting adalah menemukan keseimbangan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi, karena itu sama saja dengan menyiapkan generasi yang tidak relevan dengan zamannya. Namun kita juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada mesin.
UNESCO dalam Digital Learning Week 2024 menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada manusia dalam penggunaan teknologi AI. Artinya, teknologi harus digunakan untuk mendukung dan memberdayakan peserta didik, bukan menggantikan mereka sebagai subjek yang berpikir.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang AI dalam pendidikan adalah pertanyaan tentang apa artinya menjadi manusia terdidik di abad ke-21. Apakah cukup dengan menguasai teknologi? Ataukah justru lebih penting memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya secara etis? Saya percaya jawabannya adalah keduanya—dan untuk mencapai itu, kita membutuhkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan cara menggunakan AI, tetapi juga kapan tidak menggunakannya. Sebab, generasi emas Indonesia bukan generasi yang pandai memerintah mesin, melainkan generasi yang tetap mampu berpikir jernih ketika mesin tidak lagi berfungsi. (*)
*) Junaedi, Dosen FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, berdomisili di Sidoarjo. Email: junaedi@uinsa.ac.id