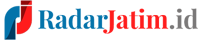Oleh Junaedi *
Kehidupan pesantren tidak selamanya damai. Di balik rutinitas mengaji dan salat berjamaah, tersimpan dinamika sosial yang kompleks: perselisihan antarsantri, kasus pencurian kecil-kecilan, pertengkaran karena salah paham, hingga pelanggaran tata tertib asrama. Ribuan santri dari berbagai latar belakang
hidup bersama 24 jam, sehingga gesekan nyaris tak terhindarkan.
Namun, bisa dibayangkan ketika seorang santri kedapatan mencuri di asrama. Apa yang terjadi? Apakah tangannya dipotong sebagaimana bunyi literal ayat hudud? Tentu tidak. Yang terjadi justru sebuah proses yang berbeda dari bunyi literal ayat jinayat: kyai memanggil pelaku dan korban, memfasilitasi dialog,
mendorong pengakuan dan pemaafan, lalu menetapkan “sanksi” berupa kerja bakti membersihkan masjid atau lingkungan pesantren, atau hukuman lain yang sifatnya mendidik.
Inilah paradoks menarik yang terungkap dalam sebuah penelitian terbaru tentang pendidikan karakter di pesantren Nahdlatul Ulama. Di ruang kelas, para ustadz mengajarkan qisas, hudud, dan ta’zir dengan presisi tekstual. Namun di asrama —di kehidupan nyata— penyelesaian konflik justru mengikuti logika yang
berbeda: rekonsiliasi, rehabilitasi, dan reintegrasi.
Islah: Jantung Keadilan Islam yang Terlupakan
Data penelitian menunjukkan temuan mengejutkan, bahwa 87% warga NU lebih memilih pendekatan islah (rekonsiliasi) ketimbang hukuman retributif dalam menyelesaikan konflik. Ini bukan preferensi marjinal, melainkan kecenderungan kultural yang mengakar dalam worldview komunitas.
Mengapa demikian? Karena Al-Quran sendiri –jika dibaca lebih dalam– menyimpan spirit restoratif yang kerap luput dari perhatian. Dalam ayat qisas (QS. Al-Baqarah: 178), pelaku pembunuhan justru disebut “saudaramu” (akhihi), sebuah pilihan diksi yang sarat makna. Pemaafan dan kompensasi disebut sebagai
“keringanan dan rahmat dari Tuhanmu” (takhfifun min rabbikum wa rahmah).
Dengan kata lain, qisas bukanlah tujuan akhir, melainkan batas maksimal. Al-Quran justru membuka ruang lebar untuk pemaafan dan pemulihan.
Pesantren: Laboratorium Alami Keadilan Restoratif
Yang menarik, pesantren sejatinya telah mempraktikkan keadilan restoratif jauh sebelum konsep ini populer di Barat. Tradisi sulh (perdamaian) dan tahkim (arbitrase) yang dipraktikkan para kyai adalah mekanisme resolusi konflik berbasis rekonsiliasi yang telah berusia berabad-abad.
Seorang pengasuh asrama putri bertutur: “Kalau ada kasus pencurian antarsantri, tentu kami tidak memotong tangan mereka. Kami mengumpulkan para santri, memfasilitasi pengakuan, mendorong taubat, dan mencari cara agar pelaku bisa menebus kesalahannya. Fokusnya selalu pada pemulihan hubungan.”
Inilah yang disebut peneliti sebagai “paradoks implisit-eksplisit”: secara eksplisit pesantren mengajarkan doktrin hukuman, namun secara implisit mempraktikkan nilai-nilai restoratif. Sayangnya, praktik baik ini belum terformalisasi dalam kurikulum.
Menjembatani Jurang: Tafsir Tarbawi sebagai Solusi
Di sinilah urgensi pendekatan tafsir tarbawi, yaknipenafsiran Al-Quran yang berorientasi pada nilai-nilai pendidikan. Di sinilah, ketika membaca ayat jinayat semata-mata bukan hanya sebagai teks hukum, akan tetapi dengan pendekatan tafsir tarbawi mengekstrak hikmah dan pelajaran moral yang relevan untuk
pembentukan karakter dari ayat-ayat jinayat.
Sebanyak 92% pakar pendidikan pesantren dalam penelitian sepakat, bahwa tafsir tarbawi efektif untuk mentransformasi pemahaman tentang ayat-ayat jinayat. Ini bukan berarti mengabaikan aspek hukum, melainkan memperkayanya dengan dimensi pedagogis.
Misalnya, ketika mengajarkan tentang qisas, ustadz tidak hanya menjelaskan syarat-syarat teknisnya, tetapi juga menggali: Mengapa Al-Quran menyebut pelaku sebagai “saudara”? Apa hikmah di balik dibukanya pintu pemaafan? Bagaimana prinsip ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren?
Bukan Impor, Melainkan Rediscovery
Penting untuk ditegaskan, bahwa keadilan restoratif bukan konsep Barat yang dipaksakan masuk ke dalam Islam. Sebaliknya, ini adalah rediscovery, penemuan kembali prinsip-prinsip yang sejatinya telah lama tertanam dalam tradisi hukum dan pendidikan Islam.
Konsep islah, sulh, diyat, dan ‘afw (pemaafan) dalam khazanah Islam klasik memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif modern. Perbedaannya, fondasi teologis Islam memberikan kedalaman spiritual yang tidak dimiliki versi sekulernya.
Prinsip Aswaja NU: tawasuth (moderasi), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i’tidal (keadilan)—ternyata berfungsi sebagai kerangka operasional dalam resolusi konflik di pesantren. Kyai, dalam posisinya sebagai mediator, menjadi “kurikulum hidup” yang memodelkan nilai-nilai restoratif.
Menuju Pendidikan Karakter yang Transformatif
Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan. Pesantren perlu menjembatani jurang antara doktrin kelas dan praktik asrama. Caranya: mengintegrasikan nilai-nilai restoratif ke dalam kurikulum formal Fiqh Jinayah.
Model Pendidikan Karakter Restoratif Berbasis Ayat Jinayat (PKR-AJ) yang diusulkan penelitian tersebut menawarkan kerangka kerja konkret. Model ini mencakup reformasi cara mengajar Fiqh Jinayah (dimensi kognitif), kultivasi nilai restoratif melalui budaya pesantren (dimensi afektif), dan pembekalan santri dengan keterampilan mediasi praktis (dimensi psikomotorik).
Yang lebih menarik, model ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Pesantren, dengan demikian, berpotensi menjadi pusat pendidikan perdamaian berbasis nilai-nilai Islam autentik.
Penutup: Merawat Tradisi, Menyambut Masa Depan
Di tengah stigmatisasi terhadap pendidikan Islam yang kerap dikaitkan dengan radikalisme, temuan ini memberikan narasi alternatif yang menyegarkan. Pesantren, jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi benteng moderasi dan perdamaian.
Kuncinya adalah keberanian untuk membaca kembali teks-teks klasik dengan mata segar, mempertahankan tradisi yang baik (al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih) sambil mengadopsi inovasi yang lebih maslahat (al-akhdh bi al-jadid al-ashlah). Bukankah ini juga prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama?
Pesantren tidak perlu mengimpor konsep Barat untuk menjadi agen perdamaian. Cukup kembali ke khazanahnya sendiri, dengan cara baca yang lebih kaya dan kontekstual. Wallahu a’lam bishawab. (*)
*) Junaedi, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: junaedi@uinsa.ac.id