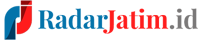Catatan untuk Pameran Tunggal Kedua Samurai Jalu
Oleh Agus “Koecink” Sukamto*
Selama ini kita terbiasa mengurung seni dalam bingkai-bingkai kayu yang kaku. Kita memakai sapuan kuas di atas kanvas yang terpajang rapi di dinding galeri, seolah kreativitas memiliki batas teritorial yang mutlak.
Namun, tren estetika global belakangan ini mulai menggugat batasan tersebut. Proses kreatif kini tak lagi berhenti di tepian kanvas Ia meluber, merayap ke sudut plafon, hingga memeluk dinding-dinding hunian kita.
Rumah, yang selama ini kita fungsikan sebagai tempat bernaung, kini berevolusi menjadi kanvas hidup. Ia bukan lagi sekadar susunan bata dan semen, melainkan sebuah medium ekspresi yang menyimpan spirit dan narasi personal yang mendalam. Ruang yang berbicara, mengapa dinding rumah memberikan spirit yang berbeda dibandingkan kanvas biasa? Jawabannya terletak pada keterlibatan emosional.
Saat seorang seniman atau penghuni rumah memutuskan untuk mengekspresikan gagasannya langsung pada dinding, ia sedang melakukan dialog dengan ruang hidupnya. Dinding tidaklah datar secara makna. Ia memiliki tekstur, menangkap bayangan matahari yang bergeser setiap jam, dan menjadi saksi bisu atas percakapan di dalamnya. Memindahkan ide ke dinding berarti mengubah skala prioritas, dari seni yang dilihat menjadi seni yang dirasakan dan ditinggali. Estetika tanpa sekat.
Dalam pameran kali ini kita akan menelusuri bagaimana proses kreatif di dalam rumah mampu membangkitkan energi baru. Hadinya energi itu, mulai dari sentuhan coretan di dinding yang memberikan ketenangan, hingga instalasi benda dari bekas hasil proses menciptakan karya. Seni di dinding rumah adalah bentuk kejujuran yang bisa memberikan rasa keindahan berbeda. Di sana, tidak ada kurator yang menilai. Yang ada hanyalah spirit pemilik rumah yang ingin mengomunikasikan gagasannya kepada setiap sudut ruangan.
Ini adalah bukti, bahwa kreativitas tidak membutuhkan ruang khusus. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk memandang rumah sebagai kemungkinan tanpa batas. Ketika dinding mulai berbicara, saat itulah rumah benar-benar menjadi cermin dari jiwa penghuninya. Ketika rumah menjadi ruang pamer lukisan, dokumentasi, dan instalasi, kesanya akan berbeda seakan dinding bercerita tentang ruang rumah yang biasanya dipandang sebagai struktur kaku yang terdiri dari semen, bata, dan kayu.
Namun, bagi Samurai Jalu dan sang ayah, Andy Rahman, rumah bukan sekadar proyek konstruksi. Ia bagaikan sebuah kanvas raksasa yang tumbuh bersama nafas penghuninya. Dalam proses pembangunan hunian mereka, garis batas antara pekerjaan bangunan dan proses kesenian melebur menjadi satu pengalaman emosional yang hangat.
Konstruksi yang melibatkan iImajinasi, selama proses pembangunan fisik rumah, sang ayah tidak membiarkan anaknya, Samurai Jalu, hanya menjadi penonton di balik garis aman. Di usia yang baru menginjak 12 tahun, remaja ini justru dilibatkan secara intim. Ketika tembok-tembok masih berupa plesteran abu-abu yang dingin, tiang penyangga, Samurai Jalu hadir dengan keberanian jemarinya.
Di sanalah proses kreativitas dimulai, tidak sekadar bermain. Ia bereksplorasi menjadikan setiap sudut ruangan sebagai saksi bisu, bagaimana seorang anak berekspresi tanpa sekat. Ia mencoret, melukis, dan menumpahkan warna, baik langsung pada dinding yang masih setengah jadi maupun di atas kanvas.
Kolaborasi Dua Generasi
Kolaborasi dua generasi, interaksi ini menciptakan dinamika yang unik. Sang ayah membangun struktur (fondasi, atap, dan dinding), sementara Samurai Jalu membangun jiwa dari rumah tersebut. Kegiatan ini menjadi ruang dialog tanpa kata antara ayah dan anak. Di saat sang ayah memastikan rumah itu kokoh berdiri, Samurai Jalu memastikan rumah itu hidup dengan imajinasi masa kecilnya yang jujur dan liar. Baginya, dinding rumah bukan lagi penghalang, melainkan media komunikasi dan setiap goresannya adalah rekaman memori tentang masa kecil dan kini yang dirayakan, bukan dibatasi.
Tidak ada kata ‘jangan mengotori tembok’, yang ada hanyalah tawaran ‘mari berkreasi bersama’. Dari ruang privat ke ruang publik, keindahan dari proses panjang ini akhirnya meluap keluar. Apa yang bermula dari coretan di dinding ruang dan kanvas, kemudian dikurasi menjadi sebuah pameran publik.
Pameran ini bukan sekadar menunjukkan hasil akhir estetika, melainkan sebuah narasi tentang proses pengasuhan melalui seni. Masyarakat diajak melihat bagaimana sebuah rumah bisa menjadi sekolah kehidupan.
Pameran karya Samurai Jalu dan ayahnya adalah bukti, bahwa kreativitas tidak harus menunggu fasilitas yang sempurna. Ia bisa tumbuh di tengah debu bangunan dan aroma cat yang menyengat. Sebuah rumah dibangun oleh tangan, namun sebuah hunian diciptakan oleh hati. Dalam setiap coretan Samurai Jalu, rumah itu bukan lagi sekadar alamat, melainkan sebuah identitas.
Proses menjadi bagian dari diri itulah pada akhirnya yang membuat karya–karya Samurai Jalu bebas tanpa beban. Seperti lukisan dalam pameran berjudul “Menari dan Berpesta”, ukuran 70cm x 90cm, acylic di atas kanvas, tahun 2025. Lukisan ini merupakan sebuah jendela yang tidak hanya memperlihatkan apa yang dilihat oleh mata, tetapi juga apa yang dirasakan oleh jiwa.
Dalam karya yang kita amati ini, kanvas Samurai Jalu mencoba menangkap esensi dari sebuah gerakan yang meledak-ledak. Melalui gaya ekspresionisme yang kental, lukisan ini menjadi sebuah narasi visual tentang energi, keberanian, dan semangat yang tak terbendung. Kekuatan utama dari lukisan ini terletak pada palet warnanya yang provokatif. Dominasi warna merah dan jingga menyulut perasaan gairah serta emosi yang mentah. Warna-warna hangat ini bukan sekadar estetika, melainkan simbol dari panasnya energi kehidupan.
Kontras yang tajam hadir melalui penggunaan warna hitam dan biru tua sebagai garis kontur, yang memberikan struktur di tengah kekacauan warna. Sementara itu, sapuan warna putih hadir sebagai aksen pencahayaan yang memberikan dimensi motion blur, memperkuat narasi, bahwa subjek ini sedang bergerak dalam kecepatan tinggi.
Teknik goresan kuas atau yang digunakan menunjukkan spontanitas yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan karakteristik ekspresionisme, di mana kejujuran emosional lebih diutamakan daripada keindahan proporsi. Cipratan warna dan garis-garis liar yang menyebar di sekitar figur utama seolah-olah adalah aura atau radiasi energi yang dihasilkan oleh gerakan subjek tersebut.
Lukisan ini adalah sebuah harmoni dari kekacauan yang terencana. Ia berhasil menangkap momen singkat dari sebuah aksi yang penuh tenaga dan mengabadikannya menjadi sebuah pengalaman emosional bagi siapa pun yang memandangnya. Fokus seniman pada jiwa dan gerakan daripada sekadar bentuk fisik menjadikan karya ini sebuah energi yang luar biasa.
Gaya lukisan Samurai Jalu, terkadang terlihat naif yang jujur dan ekspresif. Gaya lukisannya pada usia 12 tahun mencerminkan kebebasan yang belum terbebani oleh teori seni rupa formal. Dengan karakteristik utamanya abstraksi spontan, Samurai Jalu sering memulai dengan coretan secara tiba-tiba, spontan, tanpa perencanaan matang, dan didorong oleh keinginan hati atau emosi sesaat pada saat itu.
Di dinding rumah, garis-garisnya cenderung panjang dan berani, memanfaatkan ruang luas yang tidak ia dapatkan di atas kertas kecil. Dalam warna-warna primer yang berani, ia tidak ragu menabrakkan warna kontras. Penggunaan warna-warna tegas menggambarkan energi masa muda yang meluap-luap. Narasi visual raw (mentah), karena media utamanya adalah dinding bangunan yang sedang dikonstruksi, tekstur semen yang kasar dan sisa-sisa material menjadi bagian dari estetika lukisannya.
Simbolisme personal, lukisannya mungkin tidak selalu menampilkan bentuk nyata (seperti pohon atau gunung). Ia menorehkan bentuk-bentuk geometris atau figur-figur imajiner yang mewakili percakapannya dengan sang ayah atau pengalamannya melihat rumah itu tumbuh dan pengaruh dunia sehari–hari yang dilihat, atau pada waktu melakukan aktivitas tertentu bermain, lihat TV, film dan lainya.
Membangun manusia di balik rumah kolaborasi antara anak dan ayahnya, membawa pesan yang sangat mendalam bagi para orang tua dan pendidik. Rumah sebagai ruang aman bereksperimen, pesan utamanya adalah, bahwa rumah seharusnya menjadi tempat pertama di mana seorang anak merasa aman untuk berbuat kesalahan atau menciptakan kekacauan kreatif.
Dengan mengizinkan dinding dicoret-coret, ayahnya mengajarkan, bahwa nilai sebuah benda (tembok) tidak lebih tinggi daripada nilai pertumbuhan kreativitas anak. Menghargai proses di atas hasil akhir pameran publik ini bukan sekadar memamerkan lukisan yang bagus, tapi memamerkan proses kedekatan.
Ini mengajarkan kepada kita, bahwa hasil akhir (rumah yang jadi) akan jauh lebih bermakna jika setiap inci prosesnya melibatkan memori kolektif anggota keluarga. Memanusiakan anak dalam keputusan besar, kerap anak kecil dianggap pengganggu di lokasi konstruksi. Namun, dengan melibatkan Samurai Jalu, sang ayah memberikan validasi dan rasa kepemilikan. Jalu tidak merasa sedang tinggal di rumah milik ayahnya, tapi di rumah yang ia bangun bersama.
Seni sebagai medium komunikasi antargenerasi. Pesan moralnya, carilah bahasa ketiga (seni, hobi, proyek) untuk mempererat ikatan keluarga. Bukan hanya sekadar estetika naif dengan warna-warna berani yang dipamerkan Jalu di dinding itu, namun ada sebuah pernyataan sikap dari sang ayah tentang arti sebuah kepemilikan dan ruang tumbuh bagi seorang anak.
Kisah ini mengingatkan kita, bahwa melibatkan anak dalam proses orang dewasa bukan hanya soal memberikan kesibukan, melainkan kepercayaan. Samurai Jalu, di usianya yang ke-12, telah berhasil membangun rumahnya sendiri melalui warna. Ini membuktikan, bahwa seni adalah cara paling indah untuk merayakan tempat kita pulang.
Pameran ini melahirkan pertanyaan, akan dihapuskah coretan-coretan samurai Jalu yang ada pada dinding, tiang penyangga dan ruang lainnya? Ini menyentuh wilayah yang menarik antara seni, fungsi, dan makna ruang. Tentu jawabannya tidak tunggal, karena pilihan untuk menghapus atau mempertahankan coretan sang anak setelah pameran selesai sangat bergantung pada nilai yang ingin dijaga oleh keluarga tersebut.
Jika coretan dihapus, tindakan itu tidak serta-merta meniadakan makna karya sang anak. Justru, ia bisa dipahami sebagai bagian dari fase sebuah momen kreatif yang hidup dalam konteks pameran dan kemudian selesai pada waktunya. Penghapusan ini menegaskan sifat seni yang temporer, sekaligus mengembalikan rumah pada fungsi awalnya sebagai ruang tinggal.
Dalam sudut pandang ini, rumah tetap fleksibel, mampu berubah seiring waktu dan kebutuhan penghuninya. Namun, jika coretan dibiarkan dan menjadi bagian dari interior rumah, maka rumah tersebut bertransformasi menjadi arsip hidup. Coretan sang anak tidak lagi sekadar karya pameran, melainkan penanda memori, pertumbuhan, dan relasi ayah–anak.
Dinding yang biasanya netral berubah menjadi medium cerita, menghadirkan lapisan emosional yang tidak bisa dirancang di atas meja gambar. Dalam konteks ini, rumah bukan hanya wadah aktivitas, tetapi juga kanvas perjalanan keluarga.
Ada pula kemungkinan sebagian coretan dipertahankan, sebagian lainnya dihapus atau dipindahkan. Pendekatan ini menempatkan seni dan arsitektur dalam dialog yang seimbang menghormati ekspresi anak, tanpa mengorbankan kebutuhan ruang di masa depan. Pada akhirnya, keputusan tersebut bukan soal benar atau salah, melainkan soal sikap terhadap kreativitas dan ingatan.
Apakah rumah diperlakukan sebagai ruang yang selalu selesai, atau sebagai ruang yang terus bertumbuh bersama penghuninya? Selamat merayakan ruang, selamat mengekspresikan diri. {*}
*) Agus “Koecink” Sukamto, Perupa dan Penulis Seni Rupa, tinggal di Surabaya.