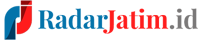Tanggapan untuk tulisan Ugo Untoro: “Menelusuri Jejak Roh yang Hilang dalam Seni Kontemporer Kita”
Oleh Arik S. Wartono
Tulisan Ugo Untoro tentang kehilangan ruh dalam seni kontemporer kita, memang menyentuh titik sensitif. Namun, narasi yang dibangunnya cenderung menyederhanakan kompleksitas seni menjadi sekadar persoalan “ketelanjangan diri” dan kehilangan kemurnian. Apakah seni benar-benar hanya tentang itu?
Untoro mengkritik seni kontemporer sebagai karya yang kehilangan denyut darah dan tetesan keringat penciptanya, seolah-olah karya seni yang baik haruslah lahir dari penderitaan dan pengorbanan yang ekstrem. Padahal, sejarah seni telah membuktikan, bahwa karya-karya besar sering lahir dari proses yang beragam, mulai dari eksperimen, kolaborasi, hingga permainan intelektual.
Kritik Untoro juga terkesan mengabaikan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penciptaan seni. Seni kontemporer sering merupakan respons terhadap realitas sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Apakah kita bisa menyederhanakan karya-karya yang mengkritik sistem kapitalisme, patriarki, atau kolonialisme menjadi sekadar persoalan “ketelanjangan diri”?
Lebih lanjut, Untoro juga mengkritik penggunaan teknologi dalam seni sebagai sesuatu yang dipaksakan. Padahal, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita dan kerap menjadi medium yang powerful untuk mengekspresikan ide-ide baru dan inovatif. Apakah kita harus menolak penggunaan teknologi hanya karena dianggap tidak “otentik”?
Seni kontemporer memang kompleks dan beragam, dan tidak bisa direduksi menjadi satu narasi tunggal. Seni tentang eksplorasi diri, tapi juga tentang masyarakat, politik, dan budaya. Seni tentang teknologi, tapi juga tentang tradisi dan warisan. Mari kita buka diri kita untuk memahami kompleksitas seni dan tidak terjebak dalam narasi simplistik.
Jiwa dalam Antropologi Filsafat
“Pisau Bedah” Ugo Untoro tentang hilangnya ruh dalam seni kontemporer kita memang tajam, tapi sempit. Narasinya cenderung menyederhanakan kompleksitas konsep jiwa dan kejujuran dalam seni. Dari perspektif antropologi filsafat, jiwa bukanlah entitas yang statis dan dapat direduksi menjadi sekadar persoalan “ketelanjangan diri” atau kehilangan kemurnian.
Konsep jiwa dalam filsafat antropologi lebih terkait dengan proses dinamis dan kompleks yang melibatkan interaksi antara individu, masyarakat, dan budaya. Jiwa adalah produk dari proses sosialisasi, internalisasi nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang beragam. Oleh karena itu, seni yang “berjiwa” tidak hanya tentang mengungkapkan luka atau penderitaan, tapi juga tentang mengeksplorasi kompleksitas pengalaman manusia.
Kejujuran dalam karya seni juga tidak melulu tentang “merawat luka” atau “membiarkan luka menganga”. Kejujuran dapat muncul dari eksperimen, keingintahuan yang mentah, bahkan komedi. Seni dapat menjadi medium untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, dan menciptakan pengalaman estetika yang unik.
Pandangan Ugo Untoro tentang kejujuran dalam seni cenderung mengabaikan kompleksitas proses kreatif dan pengalaman estetika. Seni tidak hanya tentang mengungkapkan kebenaran, tapi juga tentang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dan memperluas batas-batas pengalaman manusia.
Kejujuran dalam seni dapat muncul dari berbagai pintu, seperti:
- Eksperimen: Mencoba hal-hal baru dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada.
- Keingintahuan yang mentah: Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dan mempertanyakan apa yang sudah diketahui.
- Komedi: Menggunakan humor dan ironi untuk mempertanyakan kebenaran dan menciptakan pengalaman estetika yang unik.
- Kolaborasi: Bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik.
Dengan demikian, kejujuran dalam seni tidak hanya tentang mengungkapkan kebenaran, tapi juga tentang menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dan memperluas batas-batas pengalaman manusia. (*)
*) Arik S. Wartono, Pegiat Seni, Pendiri dan Pembina Sanggar DAUN.