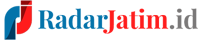Oleh Moh. Husen*
Sebenarnya isu sekolah dengan problematikanya sudah terlalu sering diperbincangkan. Apalagi sudah masuk akhir Agustus, proses pembelajaran juga sudah berlangsung.
Yang enak dibicarakan itu seputar karnaval, capeknya gerak jalan, lucunya lomba-lomba di dusun, serta kebahagiaan malam pentas seni hingga subuh. Atau membincang Pilkades di beberapa daerah, para calon legislatif, siapa capres/cawapres, atau pokoknya seputar politik dan menjelang pemilu 2024.
Namun, muncul sebuah perbincangan menarik di warung kopi yang masih saja membicarakan sekolah. Untuk melihat seberapa parah kerusakan di sebuah negara, lihatlah sekolah-sekolah milik negara, yakni sekolah negeri. Perbincangan level warung kopi ini tidak dirancang, spontan saja, dan mengalir.
Kalau pagu atau jumlah maksimal siswa yang bisa diterima di sekolah negeri hanya 200 siswa, kemudian sekolah menerima 5 siswa di luar pagu, maka akal sehat kita jadi buntu melihat kepala sekolah dan semua gurunya.
Mereka pelanggar aturan di pintu masuk pertama dalam area kesucian intelektual. Tidak bisa dibayangkan bagaimana mulut mereka bisa mengatakan keharusan bersikap sportif, sedangkan mereka justru pelanggar sportivitas paling awal.
Mungkin kita tidak tega menyebut semua itu adalah kebodohan yang nyata, apalagi sekarang arus informasi serba online dan transparan. Kita sampai bingung kenapa ada kebodohan yang sejelas itu dengan pelaku: pakarnya ilmu.
Belum lagi kalau kita mendengar kabar, masing-masing dari 5 siswa tersebut dikenakan biaya Rp 15 juta untuk bisa duduk di bangku haram itu. Apakah kepala sekolah dan para guru itu adalah pihak pertama yang mengajarkan pelanggaran di muka bumi ini?
“Tidak!” jawab seorang kawan di warkop itu.
“Pelanggar aturan pertama kali di muka bumi ini Nabi Adam,” sambungnya.
“Cangkem-mu!” teman sebelahnya menimpali.
“Nabi Adam itu,” lanjutnya, “melanggar aturan bikinan Tuhan. Sedangkan mereka ini melanggar aturan yang dibikin sendiri, yang disepakati sendiri, bertahun-tahun setiap tahun ajaran baru mereka langgar sendiri.”
“Apakah sportivitas bukan aturan yang dibikin Tuhan?”
“Dibikin Tuhan. Tapi larangan menerima siswa melebihi pagu yang telah ditetapkan, itu aturan yang dibikin mereka sendiri. Kalau tak bisa sportif, mending nggak usah ada aturan itu.”
“Kalau gitu, seharusnya perubahan yang utama dari sekolah ya? Kalau sekolahnya saja rusak, jangan heran kalau desanya rusak, kecamatannya rusak, kabupaten rusak, provinsinya rusak, dan negara rusak, begitu?”
“Begini. Kita sudah tidak bisa mendeteksi dari mana awal lingkaran kerusakan ini, apakah dari sekolah, dari pemerintah, dari masyarakat atau dari mana, kita nggak tahu.”
“Lantas?”
“Aku sendiri bukan orang baik. Aku kotor. Aku juga nggak tahu kekotoran ku ini apakah produk dari sekolahan, pemerintah atau masyarakat. Tapi menurutku, kekotoran ku karena diriku sendiri yang kalah, yang lemah.”
“Lalu minta tolong Tuhan, gitu?”
“Mengubah keburukan manusia, tidak segampang kita membuang sampah pada tempatnya. Percayalah, meskipun tak tak terlihat, proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik, selalu berjalan. Baik secara intelektual, juga secara spiritual, meminta tolong kepada Tuhan.”
Merdeka! Kopinya tolong dibayari.”
“Dan butuh waktu yang panjang untuk mengubah keadaan.”
“Yes! Waktunya mbayari ngopi.”
Mereka berdua sangat bersemangat berdiskusi saling bersahutan, meskipun ketika harus membayar kopi, mereka sering menunggu “bendahara umum” datang. {*}
Banyuwangi, 21 Agustus 2023
*) Catatan kultural jurnalis RadarJatim.id, Moh. Husen, tinggal di Banyuwangi, Jawa Timur.