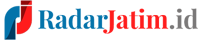Oleh MOH. GANDHI AMANULLAH
Tak terasa 11 Maret tahun 2021 ini menginjak tahun ke-10 sejak mega-bencana Jepang Timur (Higashi Nihon Daishinsai) gempa, tsunami, dan kebocoran PLTN Fukushima di Jepang terjadi. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang berjibaku dengan bencana alam.
Pengalaman dalam hal melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana adalah salah satu yang terbaik di dunia. Mereka juga kerap dijadikan rujukan bagi negara lain untuk belajar tentang bencana alam.
Namun demikian, dalam kasus mega bencana Jepang Timur 2011 atau yang lebih dikenal pula dengan 3.11 (san ten ichi ichi), Jepang tampak begitu kedodoran. Serangkaian pengalaman menangani bencana seolah belum memberikan manfaat secara maksimal ketika harus menghadapi tiga bencana yang nyaris terjadi bersamaan: gempa bumi dengan magnitude 9 dan tsunami dengan ketinggian 10-25m pada tanggal 11 dan kebocoran PLTN reaktor pertama Fukushima akibat terjangan tsunami pada tanggal 12 Maret 2011. Jumlah korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan infrastruktur akibat tsunami ternyata tetaplah tinggi.
Selain itu, puluhan ribu penduduk dalam radius 20km PLTN Fukushima harus dievakuasi untuk menghindari paparan radiasi yang hingga kini belum diijinkan kembali ke wilayah asal.
Jumlah korban jiwa yang tewas maupun hilang akibat tsunami Jepang menurut data terakhir telah mencapai angka 18.440 orang (Hiroyuki, 2017). Jumlah ini memang lebih sedikit dibanding korban tewas dan hilang karena Tsunami Aceh tahun 2004 (129.775 jiwa tewas dan 38.786 jiwa hilang), tetapi tetaplah merupakan jumlah yang besar.
Seolah menyampaikan pesan bahwa upaya mitigasi yang telah dilakukan selama ini berikut peringatan yang telah disiarkan melalui bermacam media, termasuk didengungkannya sirine di wilayah terdampak 30 menit-hingga 1 jam sebelum tsunami tiba di daratan ternyata belum memberi dampak maksimal.
Terbukti siapapun tak ada yang dapat memperkirakan bahwa tinggi gelombang tsunami yang menerjang daratan ternyata amat tinggi hinga mencapai 20m lebih, melebihi infrastrukur yang dibangun untuk menahannya. Hal ini membuktikan secanggih apapun mitigasi bencana disiapkan, bencana tetap lebih perkasa. Resiko bisa dikurangi tetapi sulit dihindari.
Pelajaran apa yang bisa dipetik dari peristiwa mega bencana tersebut? Yang pasti, perlu disadari bahwa bencana alam tak bisa lagi dianggap lagi sebuah fenomena alam yang harus dihindari. Bencana alam harus jadi “kawan” yang mau tak mau kita harus siap menyambut kedatangan kapanpun dan siap hidup berdampingan dengannya.
Terlebih mengingat Indonesia terletak pula dalam jalur cicin api Pasifik dengan frekwensi keterjadian gempa bumi sebanyak Jepang. Alat pemrediksi bencana bisa dipercanggih, tetapi belum pernah ada yang bisa memastikan dengan tepat kapan bencana terjadi.
Untuk itu, tak ada cara lain, selain harus meningkatkan upaya mitigasi dan ketahanan menghadapi resiko bencana semaksimal mungkin. Hingga kini mega bencana Jepang Timur terus diteliti dalam rangka meningkatkan ketahanan bencana, memperbaiki upaya mitigasi, dan metode penanganan bila hal serupa terjadi lagi.
Hasil penelitian menunjukkan 94,5% korban jiwa tewas dan hilang karena tenggelam terseret gelombang tsunami (Khazai, 2011). Tingkat resiko karena tsunami dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya: tingginya gelombang, daya terjang, tipe dan kemiringan pantai, mitigasi tsunami (rute evakuasi, warning system, pelatihan bencana, infrastruktur pelindung), dan faktor sikap inidividu (literasi bencana, pengetahuan mitigasi, fisik dan mental untuk melakukan evakuasi).
Tsunami Jepang 2011 menerjang tiga propinsi di pesisir pantai Jepang Timur yaitu propinsi Iwate, Propinsi Miyagi, dan Propinsi Fukushima. Meski sama-sama diterjang tsunami dengan tinggi gelombang sama antara 10-20 m, jumlah korban jiwa yang muncul berbeda-beda. Korban jiwa dan hilang di Propinsi Iwate, Miyagi, dan Fukushima secara berurutan berjumlah: 5.824 jiwa, 10.838 jiwa, dan 1.817 jiwa.
Jumlah korban jiwa di propinsi Miyagi terlihat begitu mencolok dibanding propinsi lain. Hasil dari penelitian menunjukkan hal itu disebabkan karena rentannya topografi kota-kota di pesisir Timur propinsi itu, masih lemahnya mitigasi, dan sikap penduduk dalam menghadapinya.
Topografi daerah itu landai dan minim dari infrastruktur penahan tsunami, sehingga membuat gelombang tsunami begitu mudah menerjang daratan dan pemukiman. Air tidak hanya merasuk tetapi turut menghanyutkan pemukiman mengakibatkan penduduk yang mukim sulit untuk melakukan evakuasi.
Waktu sirine peringatan memang dibunyikan 30- 1jam sebelum tsunami tiba, tetapi jangka waktu itu tetaplah terlalu singkat. Penelitian oleh Hiroyuki (2017) menunjukkan bahwa bukan berarti penduduk mengabaikan peringatan ataupun meremehkan bencana, tetapi banyak dari mereka didominasi penduduk lansia. 65,1% korban jiwa dan hilang karena tsunami adalah penduduk lansia usia 60 – 80 tahun lebih yang diperkirakan kesulitan dalam melakukan evakuasi.
Terlebih 11 Maret masih berada pada ujung musim dingin yang suhu air lautnya masih nol derajat. Banyak dari mereka depresi dan stres ketika bencana datang sehingga sulit untuk mengambil keputusan evakuasi.
Selain itu, hasil penelitian juga menjelaskan bahwa kultur masyarakat pedesaan pesisir yang memiliki jiwa guyup dan solidaritas sosial tinggi, lebih mementingkan membantu sesama ketimbang mengambil tindakan individu. Prilaku ini baik saat kondisi normal, tetapi dalam situasi bencana akan memperpendek masa evakuasi.
Kaum muda yang tinggal bersama orang tuanya yang telah lansia adalah yang paing banyak menjadi korban tsunami karena sulit melakukan tindakan evakuasi. Banyak dari mereka sebenarnya telah mengambil tindakan evakuasi, tetapi kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan keluarganya dan tak pernah kembali. Prilaku altruistik justru membuat mereka tidak survive.
Hal ini berbeda misalnya dengan apa yang terjadi di Propinsi Iwate dan Fukushima. Pesisir bernama Sanriku yang terletak Propinsi Iwate adalah wilayah yang memiliki sejarah dilanda tsunami dua kali tahun 1896 (100ribu jiwa tewas) dan tahun 1933 (3ribu jiwa tewas). Dua tsunami ini telah menyadarkan penduduk di sana secara turun menurun untuk memiliki kesiagaan akan bencana tsunami.
Dua tsunami itu juga mendorong dibangunnya berbagai fasilitas penahan tsunami termasuk menanami pesisir pantai dengan hutan pinus. Tak hanya itu, untuk melanggengkan ingatan tsunami, didirikan monumen, dibuat kisah tsunami, dan diselenggarakan festival tahunan tsunami. Misalnya mereka menciptakan jargon “tsunami ten den ko” yang artinya “saat tsunami selamatkan diri sendiri-sendiri”.
Meski berat untuk diikuti, mereka mahfum dalam kondisi genting perlu mengambil tindakan cepat yang terkadang berbau individualis. Hasilnya, jumlah korban dapat diminimalisir saat bencana terjadi. Lagi-lagi sikap, karakter, budaya suatu masyarakat menjadi faktor yang amat penting dalam mitigasi bencana.
Mengaca dari Jepang, bahwa upanya mitigasi dan penanganan bencana bukanlah usaha yang mudah. Sebesar apapun upaya mitigasi dan menyiapkan ketahanan bencana, sikap waspada adalah hal terpenting. Faktor sikap dan mindset individu berperan besar mengurangi resiko bencana khususnya bencana tsunami. Literasi, pelatihan, dan kesadaran akan bencana perlu ditingkatkan terus. (*)
*) Moh. Gandhi Amanullah, Pengamat Kejepangan, Prodi Studi Kejepangan, Unair
Ringkasan:
Peristiwa mega bencana Jepang Timur tahun 2011 yang akan menginjak tahun ke-10 pada 11 Maret 2021 ini selayaknya dijadikan momentum untuk menyadarkan kita pentingnya awas dan meningkatkan terus kewaspaadaan akan potensi terjadinya bencana alam. Kita sebagai penduduk Indonesia yang tinggal di jalur cicin api Pasifik selayaknya belajar dari Jepang saat menangani mega bencana gempa, tsunami, dan kebocoran PLTN Fukushima yang terjadi nyaris bersamaan.
Penanganan bencana di Jepang memperlihatkan bahwa upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan selama ini ternyata tetaplah belum maksimal ketika bencana terjadi terbukti masih munculnya korban jiwa tewas dan hilang yang jumlahnya ribuan.
Banyak hal yang barangkali terlewat dalam upaya mitigasi bencana di Jepang misalnya saja adalah sulitnya melakukan evakuasi pada wilayah dengan jumlah lansia tinggi. Selain itu, meski meski fasilitas mitigasi pemrediksi bencana telah canggih tetap saja tidak bisa memprediksi bahwa gelombang tsunami yang tiba mencapai tinggi yang di luar perkiraan.