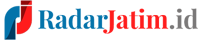Oleh MUCHLISIN
Di balik orang besar, pasti ada tangan dingin orang-orang besar yang membesarkan, tak terkecuali, Dr KH Noer Muhammad Iskandar, SQ. Sejak usia dini, kiai bersahaja ini dididik oleh ulama terkemuka, termasuk ayahnya sendiri KH Askandar, ulama kharismatik asal Banyuwangi.
Selanjutnya, estafet keilmuannya dibimbing oleh KH Mahrus Aly, saat menimba ilmu di Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatul Mubtadi’ien, Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Noer, panggilan akrab Dr KH Noer Muhammad Iskandar, SQ, juga sempat “diasuh” ilmunya oleh Kiai Muslih Futuhiyah, Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Dari sini, ia lalu melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta, sekaligus menjadi cikal bakal awal keinginannya berdakwah di kota besar bernama Jakarta.
Benteng dakwahnya ditandai dengan mendirikan Ponpes Asshiddiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 1985 silam. Dengan kesungguhan dan istiqomah, Kiai Noer mendidik para santri, hingga lambat laun muridnya mencapai 20.000 santri yang tersebar di Nusantara, termasuk di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Para alumni kini menjadi pelanjut dakwah Kiai Noer dengan berbagai macam peran dan fungsi di masyarakat. Estafet dakwah itu, terutama membangun lembaga pendidikan keagamaan berbasis pondok pesantren (Ponpes).
Kiai Noer memang luar biasa. Proses pembelajaran di Ponpes yang dipimpinnya, diterapkan keseimbangan ilmu agama (berbasis kitab kuning) dan ilmu umum (pendidikan formal). Harapannya, para santri mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Globalisasi disertai teknologi canggih, katanya, silakan dijalani. Tetapi, kekuatan agama juga harus dijaga dan ditegakkan.
Satu di antara nostalgia santri yang tak terlupakan, yakni pengajian yang rutin digelar ba’da Subuh. Selepas sholat, ia mengajarkan kitab tafsir Jalalain dan kitab Ta’limul Muta’alim, sebagai pendidikan akhlak bagi para santri sekaligus berharap diamalkan saat terjun di masyarakat.
Kaidah fiqih: Almuhafadhotu ‘alal qodimissholih wal akhdzu biljadidil ashlah (menjaga tradisi lama yang baik dan menerima tradisi baru yang lebih baik) menjadi landasan berpikir Kiai Noer dalam konsep terapan ilmu. Kendati hidup di zaman kekinian, Kiai Noer tetap berpegang teguh dengan ilmu yang telah diperoleh dari guru-gurunya. Atas dasar inilah, keberkahan dan kemajuan Ponpes Asshiddiqiyah tak terbendung. Hingga kini, sudah 12 cabang Ponpes itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai seorang guru, Kiai Noer memiliki harapan besar terhadap santri-santrinya, sebagaimana umumnya para kiai lainnya. Yang paling sederhana, Kiai Noer berharap agar para santri, ketika pulang ke kampung halamannya bisa mengajar ngaji, memimpin sholat, baca tahlil, baca doa, khotbah dan lain-lain. Ada juga yang terlihat sangat visioner, berharap kelak santrinya menjadi pengusaha, pejabat, konglomerat, diplomat, advokat dan seterusnya.
Dalam nasihatnya, Kiai Noer pernah berpesan agar santrinya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Sekilas terlihat ringan, tapi terkandung makna cukup berat, karena harus istiqomah sekaligus menjadi suri teladan bagi masyarakat.
Kiai Noer tidak berbicara soal capaian sukses yang diukur dengan kebendaan atau keduniaan, meskipun nilai keduniaan juga tak kalah pentingnya. “Khoirunnas ‘anfauhum linnas (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain),” begitu pesan yang bisa dipatrikan kepada para santrinya.
Menjadi insan yang bermanfaat bisa di mana saja, kapan saja, bisa sebagai apa saja, dan dengan apa saja. Dan, ini butuh latihan yang luar biasa, terutama menghilangkan rasa ‘paling’ pada dirinya.
Kenapa butuh latihan yang luar biasa? Sebabnya, tidak setiap orang mampu mengamalkannya. Nyatanya, banyak orang yang kaya-raya tidak mampu bersedekah. Banyak orang pandai tidak bisa berbagi ilmunya. Banyak orang terlihat salih, tapi juga tidak bisa menjadi teladan buat yang lain.
Dermawan dan Semangat Silaturrahmi
Kitab yang dipelajarinya, bukan hanya sebatas teori. Tetapi, Kiai Noer juga mempraktikkannya. Terutama, dalam menjalin hubungan baik dengan teman sejawat saat masih mondok di pesantren. Di dalam buku Saksi Kebajikan Sang Kiai, sahabatnya, KH Husein Muhammad mengisahkan kebaikan-kebaikan ulama berjuluk macan panggung tersebut.
Setelah lama tak jumpa dan melepas kangen, Kiai Husein pun berkunjung ke kediaman Kiai Noer. Sang Kiai Noer bukan hanya menyambut dengan senang hati, tetapi begitu hangat luar biasa. Bahkan, Kiai Husein mengaku diberi uang dengan jumlah yang tidak sedikit.
“Alhamdulillah, beliau memberi sangu untuk saya,” ujar Kiai Husein polos.
Sahabat sejak mondok di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur itu menyatakan, sikap ringan tangan dan tolong-menolong itu adalah kebiasaan Kiai Noer. Sikap asih itu juga bukan hanya dilakukan kepadanya saja, tetapi juga kepada tamu lainnya.
Pengakuan kemulian perilaku Kiai Noer juga diakui sahabat lainnya, Prof Dr KH Said Aqil Siradj, MA. Saat dirinya baru pulang dari luar negeri, Kiai Noer banyak membantu keluarganya. Semua anaknya dibebaskan dari biaya saat belajar di Ponpes Asshiddiqiyah, Jakarta. Kiai Noer juga memberikan jadwal mengajar bagi para guru di pesantren miliknya.
“Saya waktu itu baru tinggal di Indonesia. Belum banyak pekerjaan. Anak saya juga diberi bea siswa untuk belajar di Asshiddiqiyah,” ungkap Kiai Said blak-blakan.
Bukan itu saja, Kiai Noer juga mewajibkan semua tamu yang datang untuk makan terlebih sebelum pulang. Setiap hari, disiapi nasi plus lauk-pauknya di ruang tamu. Kiai Noer benar-benar menghargai para tamu yang datang dengan sikap terbuka dan hangat laksana saudara sendiri.
Suatu ketika, penulis bersilaturahmi ke kediaman Habib Jindan, Pengasuh Majelis Taklim Al Fachriyah, Larangan, Tangerang. Seusai Sholat Ashar, Habib Jindan duduk santai di pelataran depan rumahnya. Saat penulis menghampirinya dan mengaku santri dari Kiai Noer, betapa nampak semangat Habib Jindan menerimanya.
Ini tak lepas dari kenangan kebaikan yang dilakukan semasa Kiai Noer masih hidup. Bahkan, Habib Jindan menganggap santri Kiai Noer adalah santrinya juga.
Hubungan Habib Jindan dengan Kiai Noer memang dekat sekali, termasuk kepada keluarga almarhum. Habib Jindan mengakui, hubungan baik itu terbangun sejak zaman ayahnya, Habib Novel bin Salim Jindan masih hidup. Habib Salim dan Kiai Noer sama-sama pejuang agama yang memiliki keakraban luar biasa.
“Itu sebabnya, setiap acara di Asshiddiqiyah, saya hampir tidak pernah absen,” ujarnya.
Setelah kami berbincang lama, kemudian Habib Jindan berpesan soal silaturrahmi. Kata beliau, silaturrahmi tidak boleh putus sampai kapan pun. Ketika guru memiliki sahabat, dan guru itu sudah tidak ada (wafat), maka santri-santrinya wajib menyambung silaturrahmi dengan sahabat gurunya.
Itulah kisah kebaikan dan semangat silaturahmi Kiai Noer yang pantas diteladani, tidak saja oleh para santrinya, tapi oleh siapa pun sebagai ladang kebajikan. Semoga ilmu dan akhlak Kiai Noer memberkahi umat Islam di Indonesia, terutama bagi para santrinya. (*)
*) MUCHLISIN, Santri/Alumni Ponpes Asshiddiqiyah Jakarta, Penulis Buku ‘Saksi Kebajikan Sang Kyai’, Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Asshiddiqiyah (Iklas) Tangerang Selatan.