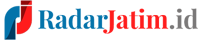Oleh Ahmad Chuvav Ibriy
Kaum santri bukanlah entitas baru dalam jagat politik di Indonesia. Sejak era pergerakan nasional hingga reformasi, mereka telah memberikan kontribusi nyata dalam menggagas, memperjuangkan, dan merawat cita-cita kebangsaan.
Para ulama pesantren, melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah — ormas terbesar di Negeri ini (tanpa mengabaikan yang lain, tentunya)– ikut membidani lahirnya bangsa ini dengan semangat kebangsaan dan kenegarawanan yang kokoh.
Namun, seiring berjalannya waktu, relasi santri dan politik mengalami dinamika. Dalam era demokrasi elektoral, santri bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga menjadi aktor politik, di antaranya sebagai anggota dewan (DPR/DPRD), kepala daerah, bahkan menteri. Hal ini membuka peluang besar, tapi sekaligus menimbulkan sejumlah tantangan yang patut dikaji lebih dalam.
Pertama, potensi moral dan basis akar rumput yang dimiliki kaum santri seharusnya menjadi modal kuat untuk membangun politik yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan publik (mashālih al-ummah). Jejaring pesantren, majelis taklim, dan komunitas keagamaan merupakan kekuatan riil yang bisa menjadi basis perubahan. Namun, potensi ini sering belum terkelola dengan baik dalam sistem politik modern yang sangat kompetitif dan pragmatis.
Kedua, fragmentasi internal santri. Perbedaan ormas, afiliasi politik, dan preferensi mahzab, membuat kekuatan politik santri sulit bersatu. Dalam Pemilu 2024, misalnya, para tokoh dan jaringan santri tersebar di semua poros calon presiden (capres). Ada yang mengusung dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran, ada yang kuat di kubu Anies-Muhaimin, sebagian lain mendukung Ganjar-Mahfud. Bahkan, tidak sedikit pesantren besar yang diam-diam terbelah di antara para alumni dan jamaahnya.
Di tingkat lokal, juga kerap dijumpai dua tokoh alumni pesantren yang bersaing keras dalam satu daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu legislatif atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), lengkap dengan gesekan dan saling serang. Ini konsekuensi logis yang mengiringi perbedaan pilihan politik di antara mereka.
Ketiga, kesiapan dalam hal sumber daya dan jaringan. Politik praktis menuntut logistik, strategi komunikasi, serta kemampuan negosiasi lintas kepentingan. Dalam hal ini, sebagian politisi santri masih tertinggal. Mereka kerap mengandalkan popularitas lokal atau simbol religius, tapi kurang dalam merawat jaringan profesional yang berkelanjutan. Bahkan, dalam konteks pendanaan kampanye, banyak tokoh santri terjebak dalam ketergantungan pada bohir atau sponsor politik yang secara ideologis tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai pesantren.
Keempat, tantangan integritas dalam politik transaksional. Di tengah arus politik yang semakin pragmatis, identitas santri tak lagi otomatis menjadi jaminan keunggulan moral. Kini, banyak politisi berlatar pesantren yang cara berpolitiknya nyaris tak berbeda dengan yang lain: sama-sama terlibat politik uang (money politics), tarik ulur kekuasaan berdimensi transaksional, kompromi politik, bahkan transaksi jabatan, baik di eksekutif maupun legislatif. Tentu ini bukan generalisasi, tapi kenyataan ini cukup membayangi harapan publik.
Dulu, dikenal tokoh-tokoh santri yang bukan hanya kuat secara intelektual dan spiritual, tapi juga disegani secara politik—sebut saja Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdurrahman Wahid, atau KH Subhan Z.E. yang mampu menjadi jembatan antara pesantren, rakyat, dan negara. Mereka bukan sekadar politisi, tapi negarawan yang membawa nilai. Maka, tantangannya kini adalah bagaimana regenerasi santri tidak sekadar masuk ke gelanggang politik, tapi mampu menghadirkan politik yang bermartabat.
Dalam momentum politik pasca-Pemilu 2024 ini, publik menunggu lahirnya kembali para politisi santri yang mampu menjadi juru bicara nilai, bukan sekadar pelobi kekuasaan. Generasi muda santri yang kini belajar di pesantren, kampus, hingga media sosial, perlu dibimbing bukan hanya menjadi pemilik identitas keagamaan, tetapi juga pejuang etika publik.
Politik bukan wilayah najis atau suci, tetapi medan jihad moral. Jika santri mampu masuk ke ruang-ruang kekuasaan tanpa kehilangan nilai, maka mereka bukan hanya menjadi bagian dari sistem, melainkan ruh yang menghidupkan sistem itu sendiri. {*}
*) Ahmad Chuvav Ibriy, Alumni Ponpes Lirboyo Kediri, Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku, Kedamean, Gresik, Jawa Timur, serta anggota Komisi Fatwa, Hukum, dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.