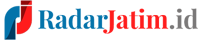Oleh Nayla Amalia Salsabila
Sunat atau mutilasi alat kelamin perempuan merupakan salah satu bentuk tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan di beberapa negara di dunia, negara miskin hingga negara berkembang. Beberapa alasan melatarbelakangi dilakukannya hal tersebut, seperti karena alasan agama, adat, budaya, dan alasan-alasan lain di luar aspek kesehatan ataupun penyembuhan.
Dengan dilakukannya sunat terhadap kaum perempuan, muncul permasalahan-permasalahan baru yang dialami “korban” berkaitan dengan kesehatan fisik maupun psikis. Sebagian masyarakat dunia juga menganggap praktik sunat kelamin perempuan melanggar hak asasi manusia HAM) dan merampas hak perempuan dalam kesehatan, keamanan, dan integritas.
Pada gilirannya, melalui PBB ditetapkan, tanggal 6 Februari sebagai hari Hari Internasional Nol Toleransi bagi Praktik Sunat Perempuan. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dunia terhadap dampak buruk dan berbahaya yang ditimbulkan oleh praktik sunat/mutilasi alat kelamin perempuan.
Dalam artikel yang berjudul Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, praktik FGM terjadi sedikitnya di 28 negara di Afrika dan beberapa negara di Asia dan Timur Tengah, termasuk Yaman dan Irak Utara. Hal serupa juga terjadi di beberapa suku etnik di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan juga di Amerika Utara, Eropa, serta suku aborigin di Australia.
Pada tahun 202, menurut data UNICEF, kasus sunat kelamin perempuan sudah terjadi pada 200 juta perempuan di 30 negara. Angka praktik sunat perempuan di Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga tertinggi setelah Ethiopia dan Mesir. Praktik tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTB, hingga Sulawesi. Prosedur yang dilakukan pun beragam. FGM di Sumatera sebagian besar menggunakan bantuan medis, sementara di daerah lain masih menggunakan metode tradisional.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2013, Gorontalo menjadi provinsi tertinggi yang melakukan praktik sunat pada perempuan. Alasannya, sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sangat sulit dihilangkan dari masyarakat. Sebagian besar sunat perempuan di Indonesia dilakukan pada bayi dan balita perempuan. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh PSKK UGM pada 2017 dilakukan pada 4.250 rumah tangga di 10 provinsi Indonesia, sebanyak 87,3 persen responden mendapatkan informasi mengenai sunat perempuan dari orang tuanya.
Pada tahun 2020, WHO dan UNFPA mengklasifikasikan praktik sunat pada perempuan menjadi 4 tipe, yaitu Tipe I, Klitoridektomi (pengangkatan sebagian atau keseluruhan kelenjar klitoris); Tipe II, Eksisi (pengangkatan sebagian atau keseluruhan kelenjar klitoris dan labia minora tanpa labia mayora); Tipe III, Infibulasi (penyempitan lubang vagina dengan memotong dan menjahit labia minora dan labia mayora); Tipe IV, Semua prosedur berbahaya yakni menusuk, menggores dan membakar area genital.
Praktik sunat perempuan menjadi masalah serius bagi perempuan, baik dari aspek kesehatan fisik maupun psikis. Masalah tersebut, di antaranya terkait kesehatan mental, kista, perdarahan, gangguan dalam berhubunganseks, nyeri terus-menerus, infeksi, gangguan berkemih, gangguan dalam persalinan.
Praktik sunat perempuan yang terjadi saat ini tidak lepas dari alasan keagamaan, adat, budaya, hingga alasan-alasan lain yang tidak berhubungan dengan kondisi medis maupun penyembuhan. Sebagian besar praktik penyunatan yang terjadi dilakukan secara tradisional dengan alat-alat tradisional yang kemungkinan besar sangat tidak steril. Hal tersebut akan sangat berbahaya bagi korban penyunatan.
Dalam agama Islam sendiri, sunat wanita bukan merupakan suatu hal ataupun perintah wajib, sehingga tidak ada masalah apabila tidak dilakukan. Berbeda dengan sunat terhadap laki-laki yang lebih banyak dampak positifnya, sunat perempuan memiliki lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan.
Pelarangan praktik sunat perempuan di Indonesia sendiri saat ini masih ambigu dan belum jelas. Masih perlu dilakukan perbaikan atau perubahan regulasi yang menjadi payung hukum terhadap larangan praktik penyunatan kelamin perempuan yang memang secara medis tidak ada manfaatnya. Selain itu, minimnya edukasi yang diberikan oleh pemerintah maupun tenaga medis membuat informasi dampak buruk praktik sunat perempuan tidak tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat masih tetap melakukan tradisinya yang turun temurun.
Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, apabila memang harus dilakukan penyunatan kelamin perempuan, alahkah lebih baik dan aman apabila dilakukan oleh tenaga medis yang profesional dengan alat–alat medis yang steril sehingga dapat menekan dampak negatif yang mungkin timbul oleh adanya tindakan penyunatan.
Praktik sunat/mutilasi alat kelamin wanita masih terjadi di negara–negara miskin dan negara – negara berkembang yang tersebar dari seluruh dunia. Tradisi keagamaan dan adat istiadat yang sudah berlangsung turun temurun tentunya sulit untuk dihentikan dalam waktu singkat. Diperlukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif dari sunat perempuan.
Peringatan Hari Internasional Nol Toleransi bagi Praktik Sunat Perempuan tentunya dapat menjadi titik balik dalam penghentian praktik sunat perempuan. Dengan adanya peringatan tersebut, diharapkan semakin meningkatnya kesadaran dan penyebarluasan dampak dari praktik sunat perempuan. {*}
*) Penulis adalah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Modern Al-Rifa’ie Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur.