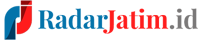Oleh Ahmad Chuvav Ibriy
Di era digital, data bukan hanya deretan angka. Ia adalah proyeksi eksistensi manusia: identitas, keyakinan, kecenderungan, bahkan harga diri. Dalam skala nasional, data adalah potret kolektif sebuah bangsa. Maka, ketika data warga negara Indonesia dialirkan ke luar negeri tanpa kontrol dan kejelasan, yang tergadaikan bukan sekadar informasi, tapi juga martabat dan kedaulatan bangsa.
Baru-baru ini publik dikejutkan oleh sikap pemerintah Indonesia yang membuka diri terhadap skema transfer data pribadi ke Amerika Serikat dalam bingkai kerja sama dagang. Pemerintah berdalih, bahwa hanya data “komersial” yang akan dialirkan. Namun, batas antara data komersial dan data strategis tak pernah benar-benar jelas. Transaksi hari ini bisa menjadi strategi geopolitik esok hari.
Dari data lahir algoritma. Dari algoritma muncul pengaruh. Maka, siapa mengendalikan data suatu bangsa, dialah yang dalam diam membentuk arah konsumsi, opini publik, bahkan cara berpikir warganya. Inilah bentuk kolonialisme digital, yang bergerakbukan dengan senapan, melainkan dengan server, kecerdasan buatan (AI), dan jaringan global yang terhubung ke pusat kekuasaan asing.
Ironisnya, kebijakan ini berpotensi melanggar UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 56 UU ini mewajibkan, bahwa aliran data lintas negara hanya boleh dilakukan jika negara penerima memiliki tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi. Amerika Serikat hingga kini belum memiliki UU perlindungan data nasional yang setara dengan GDPR di Eropa.
Pertanyaannya: untuk siapa kebijakan ini diambil? Mengapa tidak ada partisipasi publik atau transparansi dalam prosesnya? Rakyat hanya dijadikan objek, bukan subjek dalam perjanjian yang menyangkut masa depan digital mereka sendiri.
Sebagai bangsa yang hidup dari nilai etika dan spiritualitas, sudah saatnya kita menengok kembali khazanah Islam, terutama dalam prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Salah satu tujuannya adalah ḥifẓ al-‘irḍ (menjaga kehormatan). Dalam dunia modern, kehormatan itu tak hanya berbentuk fisik, tapi juga digital. Data pribadi adalah bagian dari ‘irḍ. Maka penjagaannya bukan hanya amanat hukum, tapi juga amanat agama.
Ulama besar, seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī menempatkan kehormatan sebagai pilar penting dalam struktur maqāṣid, sehingga ada ulama yang menegaskan bahwa ḥifẓ al-‘irḍ layak diposisikan sebagai tujuan tersendiri, sejajar dengan penjagaan agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Dalam konteks hari ini, penyalahgunaan data pribadi bisa merusak reputasi, menciptakan fitnah, dan membuka jalan manipulasi terhadap kehidupan sosial-politik umat.
Karena itu, ulama (di dalamnya ada MUI), akademisi, dan mahasiswa, serta santri tidak boleh diam. Mereka mesti bersuara dari mimbar ke mimbar, dari forum ke forum, agar isu ini tidak tenggelam dalam bahasa teknokratis yang membius. Literasi data harus menjadi bagian dari dakwah kontemporer. Setiap klik adalah jejak. Setiap izin akses adalah penyerahan kuasa. Dan, setiap pembiaran adalah peluang bagi asing untuk mengendalikan kita dari jauh.
Pemerintah boleh mengatasnamakan “normalisasi hubungan internasional”, tapi rakyat berhak mengingatkan, bahwa martabat tidak boleh dikompromikan demi selembar nota diplomatik atau satu digit angka ekspor.
Menjaga data adalah menjaga martabat. Dan martabat, dalam syariat, bukan barang dagangan. Allāhu A‘lam bi al-Ṣawāb. (*)
*) Ahmad Chuvav Ibriy, Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku, Kedamean, Gresik; Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik, Jawa Timur.