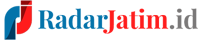Oleh Ahmad Faizin Karimi
Di tengah gegap gempita dunia politik Indonesia, masyarakat nampaknya masih terlalu mudah terhipnotis oleh pesona permukaan: senyuman manis di baliho, gestur merakyat di depan kamera, atau narasi dramatis yang menyentuh emosi. Fenomena ini berulang setiap saat, meski pemilihan umum (pemilu) sudah berjalan beberapa kali.
Tetapi, publik agaknya sulit belajar. Dari pemilihan kepala desa hingga presiden, kerap dijumpai publik yang jatuh hati, bukan pada kualitas gagasan sang calon atau kandidat, melainkan pada teatrikalitas panggung kekuasaan.
Perilaku politik masyarakat Indonesia, masih memperlihatkan gejala bias emosional yang kuat. Banyak yang menjatuhkan pilihan politik, bukan berdasar pada data kinerja, rekam jejak, atau konsistensi nilai seorang tokoh, melainkan pada kekuatan citra dan narasi emosional yang dibangun lewat media massa dan media sosial. Politisi pun pintar menangkap ini, menciptakan gimmick yang dikemas seolah autentik, padahal kerap jauh dari substansi.
Dalam psikologi politik, dikenal istilah affect heuristic, kecenderungan individu mengambil keputusan berdasarkan perasaan instan ketimbang evaluasi rasional. Dalam konteks politik Indonesia, hal ini tecermin dalam cepatnya masyarakat membentuk opini hanya dari potongan video pendek, unggahan viral, atau peristiwa sentimental yang menggugah rasa iba.
Contohnya mudah ditemukan: politisi yang menangis di depan publik dianggap tulus, yang membagikan bantuan sembako dipuja meski kebijakannya justru mempersulit masyarakat mampu membeli sembako sendiri. Masyarakat lebih mengingat gestur sesaat dibandingkan konsistensi kebijakan.
Salah satu akar persoalannya adalah lemahnya literasi politik dan kemampuan literasi data masyarakat. Meski penetrasi internet dan media sosial tinggi, hal itu belum dibarengi kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam mengolah informasi. Banyak yang masih belum terbiasa membaca laporan kinerja, memahami indikator pembangunan, atau menganalisis dampak kebijakan secara objektif jangka panjang. Kondisi ini diperburuk oleh arus informasi yang deras, namun tidak selalu akurat. Alih-alih memperkuat kesadaran data, media digital justru sering menjadi lahan subur bagi dramatisasi dan manipulasi persepsi.
Temuan kajian Status Literasi Digital di Indonesia tahun 2022, di antara penggunaan internet oleh masyarakat yang paling minim adalah untuk mengakses layanan publik/pemerintahan (71% tidak pernah), mengakses layanan pendidikan (72% tidak pernah), mengakses layanan kesehatan (69% tidak pernah), mengakses layanan keuangan/perbankan (57% tidak pernah).
Internet paling banyak digunakan hanya untuk berkomunikasi lewat pesan singkat/chatting (89% sangat sering & sering), bermedsos (62% sangat sering & sering), lihat video/dengar musik online (55% sangat sering & sering), serta browsing (54% sangat sering & sering).
Bisa dibayangkan, bagaimana orang yang jarang mengakses informasi langsung dari situs-situs penyedia layanan dan informasi publik, mendapatkan paparan tayangan pendek ter-setting dari media sosial –yang kemungkinan besar, meminjam istilah Erving Goffman– menampilkan panggung depannya. Ini sesuatu yang mudah diatur tampilannya.
Perlu ditegaskan, tidak semua komunikasi visual atau narasi emosional itu buruk. Namun, ketika itu menjadi satu-satunya alat politisi untuk membentuk citra, sementara substansi kebijakan kosong, maka publik harus waspada. Gimmick adalah alat kampanye, bukan jaminan kompetensi. Emosi boleh disentuh, tetapi nalar harus tetap jalan.
Memang, bisa jadi penilaian terhadap sebuah kinerja yang berbasis data masih mengalami bias. Misalnya saja, data tingkat kemiskinan yang mungkin saja kurang valid karena indikatornya tidak tepat. Atau data kinerja reformasi birokrasi, yang mungkin dinilai hanya berbasis administratif. Tapi bagaimana pun, lebih sulit mengakali data daripada mengakali tampilan. Lebih sulit mengakali peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), ketimbang bikin konten ‘bantu memanggul gabah di sawah’. Lebih susah meningkatkan ‘Indeks Pendidikan’ daripada bikin konten ‘beri beasiswa anak pemulung’, misalnya.
Literasi Data
Di negara demokratis, rakyat adalah hakim tertinggi. Tetapi, keputusan hakim yang baik harus didasarkan pada bukti, bukan bujuk rayu. Maka penting bagi masyarakat, khususnya kelas menengah terdidik, untuk membangun tradisi berpikir berbasis data. Sebuah keputusan politik yang baik lahir dari kombinasi antara kepekaan sosial dan ketajaman analitis.
Solusi jangka panjang tidak lain adalah pendidikan politik yang berkelanjutan. Literasi data, pelatihan berpikir kritis, serta kebiasaan membaca kebijakan dan rekam jejak tokoh harus diperluas melalui ruang-ruang pendidikan formal maupun informal. Media massa juga punya peran strategis dalam menyajikan informasi politik yang faktual, mendalam, dan tidak sekadar sensasional.
Publik tidak bisa terus-menerus membiarkan politik dikuasai oleh sandiwara. Indonesia butuh warga negara yang tak hanya tersentuh, tapi juga terlatih dalam menilai. Demokrasi yang matang dibangun, bukan oleh air mata di panggung kampanye, tapi oleh akal sehat yang tahan godaan retorika. Demokrasi yang matang, dilihat bukan dari derai tawa di depan kamera, tapi oleh pikiran kritis yang menilai secara sistematis.
Jika tidak, maka jangan mengeluh jika dari pemilu ke pemilu, kita hanya akan keluar dari mulut buaya masuk ke cengkeraman serigala bertopeng singa. {*}
*) Ahmad Faizin Karimi, Pegiat Literasi dan Peneliti Faqih Usman Center (FUC).