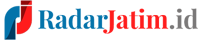Sebuah Narasi Masa Lalu – Kini
Oleh Anang Prasetyo
Aku menafsir kembali kisah cinta abadi ini, dalam karyaku
Dengan setting lokasi pertemuan mereka setelah terpisah berpuluh purnama,
di Cumbri yang berkabut, perbukitan perbatasan Ponorogo Jawa Timur dan Wonogiri
Jawa Tengah
(Aliya Murdoko 2025)
Narasi Panji ala Aliya itu demikian kuat. Menggugah kesadaran nurani insani serasa seolah tersengat. Kesadaran akan ilmu dan tafsir laku masa lalunya begitu mengharu-biru. Demikian yang menjadi garis bawah deskripsi saya tentang lukisan Aliya.
Sengaja, narasi Aliya itu saya jadikan penghantar di awal tulisan ini sebagai bukti, bahwa pelukis remaja ini memiliki “daya linuwih” yang tidak dimiliki oleh pelukis sepantarannya. Tidak banyak pelukis, apalagi pelukis muda remaja, menorehkan kuas dan cat di kanvas dengan gagasan kuat. Sebab, yang Aliya lakukan adalah sedang menjalankan apa yang oleh para leluhur kita sebagai suatu tirakat kebudayaan, atau saya memberi nama: laku lampah. Laku sebagai olah jiwa, meditasi, atau nilai spiritualitas, sebagai sebuah perenungan mendalam. Sementara lampah, dipahami sebagai suatu jalan atau metode teknik dalam menjalani “laku” tadi.
Dalam ranah kebudayaan, laku lampah ini seolah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pelaku kebudayaan. Entah wajib atau tidak silakan untuk diperdebatkan. Tapi setidaknya, laku lampah ini adalah suatu pola keniscayaan. Tentu saja, dengan memakai ragam metodologi.
Metode ini, sangat pribadi. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Unik dan menciri khas.
Kadang demi menggapai masa lalu untuk kemudian melakukan tafsiran kontemporer, langkah dan caranya demikian unpredictable. Di sini ada wilayah dialektis yang tak bisa dimonotypekan. Sebabnya, ia demikian personal.
Ruang dialektis ini, tak pelak, hanya bisa dicapai dan tercapai jika seseorang mau menoleh ke belakang. Melihat masa lalu untuk kemudian merancang masa depan. Analoginya, seperti halnya orang menarik tali busur panah ke belakang. Untuk kemudian melepaskan busur anak panah melesat jauh ke depan. Bahkan, kalau bisa sejauh-jauhnya. Tergantung sasaran mana yang akan dituju. Saya melihat, disadari atau tidak oleh dirinya, Aliya sedang melakukan upaya itu dalam semua lukisannya.
Langkah Nyata
Saya pernah menulis demikian
“Filosofi laku lampah ini pada akhirnya, tiba pada suatu pemahaman, bahwa setiap manusia sejatinya sedang melakukan perjalanannya masing-masing”
(Anang Prasetyo, 2018 h. 63)
Tak banyak pelukis yang mengangkat tema Panji. Apalagi itu anak-anak dan remaja. Karena itu, catatan dan literasi tentang ini layak untuk diketengahkan. Sebagai bentuk telaah atas paradigma, worldview, alam pandang keilmuan dan praksis kesenirupaan. Karya Panji ala Aliya dengan tafsir terhadap masa lalu, itu perlu dieksplanasi lebih jauh.
Sesekali cobalah bertanya kepada Aliya Murdoko. Sang anak yang beranjak remaja ini, apa dan siapa yang mendorong dia untuk melukis dengan tema Panji. Ini penting ditanyakan. Apakah hanya karena faktor geografis, bahwa ia tinggal di kota Malang. Artinya, ia bermukim di sana. Menghirup aroma dan sastra dan rupa Panji dalam atmosfer yang sangat kuat di setiap sudut kotanya. Ataukah ada faktor lainnya?
Anak remaja ini, usia SMP-SMA (dia baru saja masuk kelas X SMA) memang sedang tertantang untuk sesuatu hal yang baru dalam perspektif menjelajah kebaruan. Jika sekarang ia pada titik mengeksplorasi teknik realis, maka pada hakikatnya ia sedang belajar untuk suatu teknik melukis yang baru, sebagai suatu etape penjelajahan estetiknya.
Sangat boleh jadi, para pengamat seni yang melihat perkembangan lukisan Aliya, boleh saja ragu dengan kemampuan teknik Aliya ini. Apalagi dalam deformasi bentuk yang dimilikinya sejak usia anak-anak bahkan usia balita Aliya. Padahal, karya Aliya justru mengalami progresivitas yang berjalan dan terus berkembang.
Aliya, menurut penuturan Arik S. Wartono, sang guru pembina, belajar di sanggar DAUN sejak usia 3 atau 4 tahun, saat usia masih playgroup dan masih ngedhot. Sehingga, Arik S. Wartono sangat paham, sebagaimana kepada muridnya yang lain, selalu mencoba mengikuti setiap gerak artistik dan estetika anak didiknya. Selain naluri fitrah sifat: Yaa Rohman, Yaa Rohim titipan asmaul husna-Nya itu, mengalir deras dalam hembusan nafas mendidik Arik, itu juga mengalir sebagai suatu naluri keguruan yang menjadi bagian dari proses pendalaman kejiwaan Arik Sang Guru.
Proses pematangan teknik ini pada akhirnya, dimiliki dan pasti dialami semua muridnya. Kepada Aliya pun demikian halnya. Karena, demikian penuturan Arik, kalau anak tanpa melewati periode realis juga berisiko pada kematangan tekniknya. Seakan-akan kurang kaya dalam bentuk, ruang dan dalam hal apa pun lainnya.
Rupa Panji dalam Jiwa Aliya
Yang jelas warna lukisannya sangat kuat dan berani. Garis yang Aliya torehkan juga tegas. Hitam merah ditorehkan dengan keberanian yang jelas. Ini tercermin dalam lukisannya yang berjudul “Semirang” (2025) dan “Panji Semirang” (2025). Itu artinya, secara psikologis, Aliya adalah tipe anak yang memiliki karakter tegas dalam bersikap. Setegas garis demarkasi ideologi berkeseniannya.

Pelukis remaja, Aliya Murdoko
Pertanyaannya adalah kekuatan apa yang mendorong Aliya melukis dengan tema Panji? Biarlah itu enjadi misteri untuk kemudian esok saat bertemu untuk ditanyakan kepadanya. Atau jika misal tidak ditanyakan sekalipun, sejatinya masing-masing kita menapaki laku atau jalan yang sebenarnya mengalami pengulangan secara historikal budaya. Genetika bangsa Nusantara selalu inheren dan natural terbawa dalam setiap perjalanan manusia Indonesia. Demikian pula pada diri Aliya dengan karya-karyanya.
Dalam catatan kuratorial Panji Pameran Besar Seni Rupa 2018, dinyatakan, bahwa cerita Panji sebagai dasar konsep penciptaan seni rupa kontemporer memiliki tantangan tersendiri. Tantangannya terletak pada perbedaan pemahaman, penghayatan, dan tafsir para perupa mengenai historisitas cerita yang populer di Jawa Timur itu. Yang secara faktual meninggalkan jejak-jejak ekspresi seni yang bermacam-macam; relief di sejumlah candi, kesenian wayang topeng, wayang beber, batik tulis dsb.
Sebagai pemegang estafet rupa, visualisasi dengan mengangkat tema Panji adalah, pada akhirnya, seperti yang saya bilang di atas, adalah suatu keniscayaan. Baik seni rupa, seni musik, sastra dan budaya dari peradaban besar Panji yang telah melegenda sedunia itu. Pada akhirnya, ia kini mengejawantah dalam setiap napas kesenian, khususnya di Malang. Lebih spesifik lagi pada diri Aliya dan karyanya.
Sebagai pelukis, kekuatan “magis visual” Aliya Murdoko, ada pada lukisan berjudul “Cumbri Gelang-gelang 1&2″ (2024, 2025). Sebagaimana tesis saya di atas, sebagai laku lampah. Ternyata ia mewujudkan karyanya dengan melakukan ‘lelaku dan lelampah‘ langsung di gunung (perbukitan) Cumbri. Luar biasa!
Penjiwaannya dapat.
Namun, buru-buru harus saya susuli, sebagai sebuah prolog pencitraan visual, pencapaian ini harus terus diasah. Meskipun pencapaian karya itu sendiri, faktanya, dan memang ternyata sungguh tidak mudah. Bagaimanapun respon gagasan, alias tafsir terhadap sebuah peradaban besar, itu sah dan Aliya memang wajib melakukan itu.
Sebagai anak yang beranjak dewasa -yang sekali lagi- menghirup udara Panji, nafasnya adalah Panji, detak jantung dan urat nadinya adalah Panji. Dan setiap detak jantungnya yang menggemuruh adalah peradaban Panji. Ibaratnya, Aliya adalah hasil “anak peradaban” dari perkawinan Panji Semirang dengan Dewi Sekartaji, persis seperti lukisan yang ia lukis dengan judul tersebut. Dan naga-naganya memang ada tanggung jawab besar Aliya untuk mengemban amanah peradaban dalam citra apapun juga.
Sebagai pencapaian estetik sekaligus renungan visual lanjutan, saya menangkap ada kekuatan Aliya yang unik, ada pada lukisan berjudul “Pelarian Candra Kirana“, cat minyak dan akrilik di atas kanvas, 60×120 cm, 2025. Digambarkan di situ, seorang perempuan yang sedang menaiki kuda putih. Seolah ia melayang memutari pusaran air atau angin yang ada di langit. Lukisan itu sesungguhnya memiliki daya mistis, dan daya magnet spiritualitas yang sangat kuat dan demikian lekat. Gagasan imajinernya saya rasa, melampaui usianya.
Dahsyat! Pilihan warna dan dominasi garisnya demikian hidup. Kesan nglangit dan nglangutnya dapat. Kata ‘nglangut‘ ini mengingatkan saya pada lukisan alm. Amang Rahman. Saya terpaksa harus sedikit kembali ke masa silam. Serius, tiba-tiba saya jadi ingat dengan skripsi saya yang mengangkat lukisan Amang Rahman Zubair, seorang pelukis senior Surabaya.
Judul skripsinya, Spiritualitas Warna Lukisan Amang Rahman, saya tulis tahun 1995. Warna-warni lukisan maestro perupa dari Surabaya, Amang Rahman demikian mengalun lembut seperti desir angin yang memagut.
Nah, kesan orisinalitas samanya rasa, itu yang saya dapati dari lukisan karya Aliya tersebut. Sungguh mengagumkan memang, betapa lukisan Aliya mampu menghantarkan getaran rasa yang demikian menghunjam ke dasar jiwa saya.
Jika ditarik pada tataran nilai spiritualitas, seakan saya juga ditarik ke 2017 silam. Saat saya melakoni laku lampah, sebuah peristiwa jalan kaki 15 hari dari Tulungagung ke Salatiga. Sebuah napak tilas kakek saya, Muhammad Bunyamin, yang juga berjalan kaki dari Bagelen Purworejo ke Trenggalek.
Di perjalanan antara Ponorogo ke Magetan, seolah saya melihat pemandangan para malaikat-Nya menari-nari lembut di langit. Warnanya putih dengan kesan warna biru muda. Ada nuansa kehijauan. Kesan kuat itu yang saya lihat, dan menancap kuat pada lukisan Aliya Murdoko ini. Sangat subjektif memang. Namun, meminjam istilah Mikke Susanto di buku Jeihan, di sana ada kebenaran rasa. Dan, rasa memang tak bisa dibohongi.
Sekarang perhatikan perspektif yang Aliya ambil. Rata-rata yang memiliki kadar spiritualitas adalah yang bird eye. Nampak atas. Seolah itu sudut pandang mata Tuhan yang melihat. Itu jika Tuhan dipahami, bahwa Dia di atas sana. Padahal, pada hakikatnya Tuhan ada dalam diri kita.
Maka, tidak berlebihan kiranya jika saya demikian terpikat melebihi lukisan karya-karya Aliya lainnya. Tanpa bermaksud, sekali lagi, alih-alih menarasikan panjang lebar tentang serial Panji-nya yang bernuansa warna hitam, merah. Di dalam lukisan ini Aliya menemukan peak spiritual. Puncak spiritualitas dan kekayaan visual yang mencengangkan!
Demikian pula lukisan lain yang membuat saya terpana adalah lukisan Aliya dengan tema pemandangan alam. Judulnya “Cumbri Gelang-gelang“, cat minyak dan akrilik di atas kanvas, 100×100 cm, 2024. Aliya Murdoko mampu menampilkan sisi estetik lain yang demikian halus. Perspektif mata elangnya mampu menangkap pemandangan dari atas langit. Seakan Aliya membaca dengan teliti setiap lekukan pepohonan dan perbukitan yang hijau dan begitu menentramkan hati.
Namun, sebagai catatan kepenulisan sebuah sejarah visual, adalah haknya Aliya. Apa pun pilihannya kembali kepada pelukisnya sendiri. Laku visualnya masih teramat panjang dan sungguh berliku. Pilihan warna, diksi rupa, serta tema lukisannya masih terlalu dini untuk dijustifikasi. Biarkan ia bermain-main dengan gagasan dan ide briliannya seperti yang terlihat dari karya-karyanya.
Sehingga seperti tulisan awal saya di atas, “Filosofi laku lampah ini pada akhirnya, tiba pada suatu pemahaman, bahwa setiap manusia sejatinya sedang melakukan perjalanan masing-masing”. Maka laku rupa Aliya masih teramat panjang, Insya Allah. Semoga Tuhan Yang Maha Kreatif (Yaa Mushowwir) dan Yang Maha Mencipta (Yaa Kholiq) selalu mendampingi dalam laku lampahnya, Aamiin.
Kelak sejarah kesenirupaan Indonesia dan dunia yang menjadi saksi dan mencatatnya, sebagai tinta emas kiranya.
Selamat menjelajah dalam perjalanan visual Aliya! Kami menunggu debaran spiritualitas yang termaktub dalam warna di kanvasmu! (*)
Tulungagung, 30 Juli 2025
Sumber bacaan:
- Katalog PANJI Pameran Besar Seni Rupa 2018
- Laku Lampah ekspresi jiwa dalam puisi dan rupa. 2018. Penerbit Nuha Publishing
*) Anang Prasetyo, Guru, Pelukis dan Trainer Menggambar dengan Memori Bahagia. Sedang menginisiasi gerakan umroh dengan gagasan Menggambar Kakbah di Makkah.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.